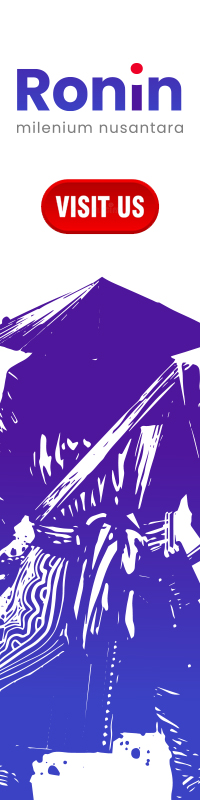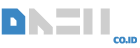Oleh: Teguh Firmansyah
Semalam kami masih bercanda mesra, kini ia harus terbaring di rumah sakit tak berdaya.
DERING handphone berbunyi nyaring. Aku bangun dengan tergagap. Tak biasanya ada telepon pagi-pagi buta seperti ini.
Ku coba menengok ke arah dinding. Jarum jam baru menunjukkan waktu pukul 04.00 pagi. Sayup-sayup terdengar suara orang mengaji dari masjid tak jauh dari apartemenku tinggal.
Aku berdiri dan langsung melihat telepon genggam di atas meja yang biasa kupakai untuk menulis. “Randi,” nama itu terlihat di layar ponsel. Seketika jantung ini langsung berdegup cepat. Rasa kantuk hilang, dan kubertanya-tanya di dalam hati. “Ada apa Randi pagi-pagi ini menelepon?” “Apakah ada suatu hal yang darurat?”
Pertanyaan itu terus muncul di kepala, sampai akhirnya aku pun mengangkat telepon itu.
“Assalamualaikum, ada apa Randi?” tanyaku dengan pelan.
Namun bukan Randi yang menjawab, melainkan suara seorang wanita yang sudah tak asing bagiku. Ya, suara mezosopran dan campuran logat jawa khas Solo yang membuatnya selalu mudah diingat.
“Dik Rima, nuwun sewu enggeh, mau mengabarkan, Randi mendadak masuk ke rumah sakit di ICU,” ujar wanita itu dengan suara sedikit terbata-bata.
Wanita tersebut tak lain adalah bulik Randi. Kami biasa memanggil beliau Bulik Jum. Sontak aku kaget mendengar kabar itu, bak sambaran petir di siang bolong. Aku coba menarik nafas, dan berusaha menenangkan diri.
“Ada apa dengan Randi Bulik? Kenapa bisa ia sampai ke ICU?,” tanyaku.
“Anu, nuwun sewu Dik, Randi sesak nafas, nafasnya susah, sekarang di rumah sakit umum Tangerang,” jawab Bulik.
Bulik tak banyak bicara lagi. Ia hanya menyarankanku agar segera datang ke rumah sakit. Aku pun tak pikir panjang, mengambil kerudung hitam yang biasa ku gantung di balik pintu.
Kubalut kaos tidur kebanggaanku dengan jaket merah marun pemberian Randi. Kubuka layanan aplikasi transportasi daring, dan memesan layanan taksi dengan tujuan Rumah Sakit Umum Tangerang.
Jarak antara rumah sakit dan apartemenku di kawasan Serpong sekitar tujuh kilometer. Pada jam kerja, mungkin butuh sekitar 45 menit untuk sampai ke rumah sakit. Namun karena waktu masih sangat pagi perjalanan bisa jauh lebih cepat.
Dan beruntung, aku langsung mendapatkan driver. Kubuka pintu taksi daring itu dan kemudian memberi pesan ke sopir, “Cepat ya pak,” pintaku.
Sang driver mengiyakan. Dia tancap gas tanpa ragu. Polisi tidur diterabasnya dengan hanya sedikit menurunkan kecepatan. Spedometer menunjukkan kecepatan 60 km per jam. Goyangan cukup terasa.
Aku berusaha untuk tenang. Namun tetap saja, pikiran ini berkelibat ke mana-mana. Ya, baru semalam kami saling bercanda mesra di ujung telepon, meski Randi sebetulnya memang tidak dalam kondisi prima.
Ia sempat demam, dan sedikit batuk. Namun Randi berbicara tetap dengan gayanya yang jenaka. Anak pertama dari dua bersaudara itu bahkan tak sekalipun menyinggung penyakitnya. Dan lagi-lagi, ia kembali membuatku tersenyum dan tertawa.
“Sebelum ketemu kamu, aku kehilangan sesuatu, tapi setelah ketemu kamu. Aku menemukannya,” kata Randi.
“Apa itu mas,” tanyaku dengan penuh penasaran.
“Tulang rusuk,” goda Randi dengan gombalannya.
“Ah dasar kamu mas!! gombalannya basi. Kamu nyontek di Google ya? hahaha …”
Kami pun tertawa lepas melepaskan kepenatan akibat kerja di rumah yang sudah berjalan tiga hari ini. Kami tertawa seolah hanya kami berdua di dunia ini. Tapi, bagaimanaa pun aku tetap menghargai usaha Randi. “Terima kasih usahanya mas, aku kasih nilai 7,5 deh .. hihihi ..,” candaku.
Randi sedikit menahan tawanya. Tapi ia belum berhenti. Kini Insinyur jebolan universitas ternama di Bandung itu pun melanjutkan rayuan-rayuannya dengan syair-syair yang lebih romantis.
“Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dik … seperti kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu… Aku ingin mencintaimu dengan sederhana… seperti isyarat yang tak sempat dikirimkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada… ”
Sekarang aku terenyuh. Aku benar-benar tak kuasa menitikan air mata. Aku terharu dengan kesungguhannya. Aku terharu akan kerja kerasnya. Aku terharu dengan buaian-buaiannya yang membuatku merasa sangat teristimewakan.
Ia selalu membuatku tersenyum. Kalau pun sedang bersedih, Randi memilih untuk menahan diri dan tetap tegar dihadapanku.
“Mas kali ini, aku kasih kamu nilai 10, syair yang indah mas. Dan aku berharap kamu akan mencintaiku apa adanya. Seperti syair yang kau lantunkan,” kataku seraya menambahkan, “Semoga Allah meridhoi kita mas.”
Syair ini dibuat penyair legendaris Indonesia Sapardi D Darmono. Syair yang berjudul ‘Aku Ingin’ ditulis Sapardi pada 1989. Pada tahun yang sama Sapardi juga membuat puisi fenomenal ‘Hujan di Bulan Juni’.
“Saya selalu berjanji dik, saya akan menjagamu sampai nafas ini terhenti. Saya akan menjagamu sampai jiwa ini tercerabut dari jasad. Kita akan senang bersama, kita susah bersama, kita bangun mimpi kita bersama.” tutur Randi meyakinkan.
Kami berbicara sekitar 20 menit. Berbicara dari satu topik ke topik lainnya. Dari rencana satu ke rencana lainnya. Kami pun sejatinya akan menikah pada bulan April ini.
Namun akibat pandemi virus Corona, semua rencana itu gagal dan kami terpaksa menundanya hingga Desember. Kami meminta penjadwalan ulang ke pihak gedung dan katering. Undangan yang sudah siap kami edarkan pun terpaksa kami tahan dulu.
“Maaf sudah sampai mba,” suara sang driver mengakhiri lamunanku. Kini aku kembali ke dunia ‘nyata’.
Kurapihkan sedikit kerudung dan mengancingkan jaket bagian bawah yang lepas.”Iya, baik terima kasih pak.”
Aku bergegas. Kubuka pintu mobil, dan menuju ke ruang ICU. Sudah lama aku tak ke rumah sakit ini. Terakhir pada 2010 lalu saat menjenguk saudara yang kebetulan sedang sakit demam berdarah. Banyak sekali yang berubah terutama di fisik bangunan.
“Boleh tahu di mana ruang gawat darurat sus,” tanyaku kepada seorang perawat jaga yang berada di ruang pendaftaran.
Sang suster pun dengan ramah menjawab, “Mba bisa lewati lorong itu, lalu belok ke kanan, di sana letaknya ICU.” “Terima kasih Sus.”
Aku berjalan melewati sebuah lorong. Lampu neon berpendar, tanda hari masih gelap. Hanya beberapa orang yang terlihat. Mereka sebagian besar adalah penunggu pasien.
Dari jauh kulihat tulisan “ICU”. Aku pun mempercepat langkah kaki ini. Di sana tampak Bulik Jum, Ibu Siti yang tak lain ibunya Randi, dan Aris adiknya Randi.
Ketiganya duduk di kursi depan ruangan unit gawat darurat dengan wajah penuh kecemasan. Saya datang mendekat, dan Ibu Siti langsung berdiri memelukku penuh erat. “Randi-Randi nak …,” kata Bu Siti yang tak kuasa menahan tangis
“Randi semalam demam tinggi, dan jam 03.00 sesak nafas. Awalnya kami kira sesak nafas biasa, tapi ternyata bukan.”
Ibu Siti sesegukan. Aku pun tak sanggup menahan kesedihan. Air mata jatuh tanpa aba-aba. Ku coba menyeka, tapi tetap tak bisa tertahan “Jadi sekarang bagaimana kabarnya Randi bu,” tanya ku memberanikan diri.
Bulik Jum menyela, “Nuwun sewu Dik, Randi saat ini sudah tak sadarkan diri. Dokter bilang kondisinya kurang baik, dan ia dibantu oleh ventilator.”
Bulik menuturkan, tim dokter yang menangani Randi juga tak sembarangan. Dokter dan perawat mengenakan alat pelindung diri berwarna putih seperti pakaian astronot. Dokter bilang bahwa Randi sudah masuk ke ruang isolasi. Dia sudah masuk dalam daftar Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona.
Aku pun tertegun. Pikiranku semakin kacau. Dunia seperti mau kiamat. Bagaimana mungkin seorang Randi bisa tertular virus yang belum ada obatnya tersebut. Apakah ia benar-benar positif? Apakah ia bisa selamat?
Hal yang membuat Rima semakin kaget adalah usia Randi yang boleh dibilang masih muda. Pada Desember mendatang Randi baru berusia 30 tahun. Randi juga tidak mempunyai rekam penyakit bawaan.
Seorang dokter jaga mengenakan APD lengkap mendekati kami. “Ibu keluarga Randi,” tanya dokter tersebut. “Iya Dok,” jawab bu Siti sambil kembali menanyakan kondisi anaknya.
“Begini Bu, pasien belum sadar, kondisinya masih kami pantau. Kita sama-sama berdoa semoga ia bisa melewati semua ini.” Sang dokter lantas mengharapkan pihak keluarga untuk pulang dan mengarantina diri. Pihak rumah sakit khawatir keluarga pasien terpapar oleh virus mematikan tersebut.
Kami awalnya menolak. Namun dokter dan rumah sakit mendesak supaya kami segera pulang karena khawatir membahayakan yang lain.
Di sini, aku kembali tak kuasa menahan tangis. Mengapa hal ini terjadi kepada Randi? Mengapa hal ini terjadi kepada tunanganku? Mengapa Randi harus ditinggalkan sendiri saat ia harus berjuang melawan penyakit ini?
Pukul 04.45 pagi. Azan Subuh menggema dari sebuah Masjid di lingkungan rumah sakit. Ingin rasanya aku dapat memenuhi panggilan itu. Ingin aku bersujud dan memohon petunjuk-Nya. Ingin aku menangis sekencang-kencangnya. “Ya Allah, cobaan apa yang berikan kepada kami.”
Di sudut ruangan Rima menerawang. Ia menatap ke jalanan dari jendela apartemennya di lantai 15 di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Mobil sudah ramai berlalu lalang, meski belum normal seperti sebelum pandemi.
Orang-orang sudah beraktivitas, walau tetap mengenakan masker. Warga pun sudah memadati kembali pusat-pusat perbelanjaan. Pedagang kaki lima juga sudah berjualan. Ekonomi perlahan bangkit.
Namun tidak halnya dengan Rima. Ia kini lebih banyak berdiam. Tak ada canda maupun tawa. Sepulang kerja, ia langsung balik ke apartemennya. Sejumlah rekan di kantor beberapa kali mengajaknya untuk hang out. Tapi ia menolaknya selalu dengan alasan yang sama. “Aku capek.”
Hari ini, Minggu 6 Desember 2020, sejatinya Rima duduk di pelaminan bersama sang kekasih hati, Randi. Hari ini semestinya ia berbalut kegembiraan, menerima undangan para tamu, berfoto mesra, berkumpul dengan keluarga maupun teman-teman dekatnya.
Hari ini, seharusnya ia sah menjadi istri sang Insinyur. Menapaki awal hidup baru, memiliki rumah, dan membesarkan anak-anak. Impian yang kerap mereka bicarakan saat malam sebelum tidur.
Rima selalu teringat pesan akhir Randi di setiap ujung pembicaraan mereka di telepon. “Dik, mas janji akan selalu disampingmu.”
Namun kini tidak ada lagi ucapan itu. Semua terasa hampa. Randi tidak berhasil selamat saat perjuangannya melawan virus Corona. Ia hanya lima jam di rumah sakit. Randi tidak dibawa pulang ke rumah.
Tak ada prosesi pemakaman pada umumnya. Jenazahnya langsung dikuburkan oleh petugas yang mengenakan pakaian lengkap alat pelindung diri. Rima bahkan tak punya kesempatan untuk mengantarkannya di tempat peristirahatan terakhir.
Rima memegang undangan pernikahan yang belum sempat dibagikan. Ia perlahan membaca kembali undangan itu. Kata-kata yang pernah mereka sepakati dan susun bersama lewat diskusi panjang.
Ya Allah, dengan Rahmat dan Ridho-Mu perkenankanlah tautan cinta buah hati kami :
Rima Melati (Putri ke-2 dari Bpk Mahfud & Ibu Sunarti)
Dengan
Muhammad Randi, (Putra ke-1 dari Bpk Alm Sugiono & Ibu Siti Fatima)
Rima tak sanggup melanjutkan. Ia kembali menangis sejadi-jadinya. Ia terduduk, menekukan lututnya , memeluk erat dengan kedua tangan. Ia berteriak, “Randi …..!”
Tangerang, 28 Maret 2020, dari Rumah Cendana