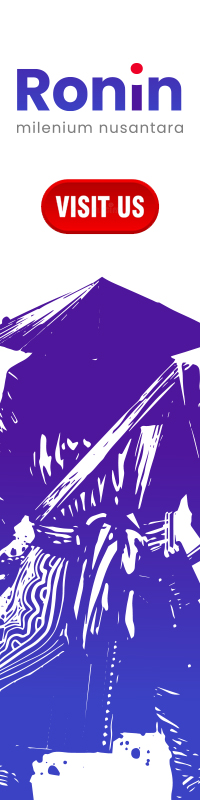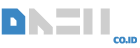Oleh: Jan Prince Permata, SP, MSi, Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Presidium GMNI 2002-2005, Sekretaris Anggota Wantimpres RI
Sejak dua dekade terakhir menjelang abad 20, dunia mengalami berbagai perubahan global fundamental yang dampaknya secara tidak terelakkan mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Gelombang perubahan global yang hingga dewasa ini terus berlangsung dan bergerak semakin cepat itu telah membawa masyarakat dunia pada suatu pengalaman dan kehidupan baru yang penuh tantangan.
Menjelang akhir dekade 1980-an, kita menyaksikan serangkaian perubahan besar dunia yang mendorong munculnya peta baru kekuatan politik global. Ancaman yang mencekam akibat perang dingin yang berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II, tiba-tiba lenyap bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan imperium Uni Soviet secara cepat dan tidak terduga. Dengan berakhirnya perang dingin itu maka dinamika hubungan internasional antar negara mulai memasuki suatu babak baru.
Semula dinamikanya lebih banyak ditentukan oleh adanya realitas persaingan kekuatan politik global bi-polar antara Blok Barat yang dimotori Amerika Serikat dan Blok Timur yang dikendalikan Uni Soviet. Sejak negara imperium komunis itu bubar, dinamikanya lebih mencerminkan adanya perkembangan kekuatan politik global yang multipolar yang nyaris tanpa pola tetap dan pasti.
Oleh karena itu harapan semula bahwa runtuhnya kekuatan imperium Uni Soviet akan menjelmakan suatu wujud dunia yang lebih damai, pada kenyataannya malah berbeda sama sekali. Dunia bukannya semakin sepi dari ketegangan dan konflik internasional, tetapi sebaliknya ketegangan dan konflik terus berlangsung di berbagai belahan dunia. Bahkan memasuki abad 21, dinamika ketegangan dan konflik internasional malah menunjukkan gambaran yang semakin kompleks, rumit, multidimensi, serta sulit diprediksi dan diperkirakan polanya.
Di sisi lain, berakhirnya perang dingin tersebut di atas, pada awalnya membawa harapan baru bagi kemajuan pembangunan global, terutama bagi mereka yang percaya pada model pembangunan yang berlandaskan ekonomi pasar bebas (free market economy). Puncak dari harapan itu, antara lain, tercermin dari pandangan futurolog, Yoshihiro Francis Fukuyama, dalam karya bukunya yang sangat popular, berjudul bukunya ‘The End of History and The Last Man’, yang terbit tahun 1986.
Isi buku itu pada dasarnya menggambarkan bahwa pertarungan idiologi dan pemikiran yang mewarnai sejarah masyarakat global, terutama sejak usainya Perang Dunia II, telah berakhir; dan dengan begitu perjalanan pembangunan global ke depan tidak lain merepresentasikan perkembangan lebih lanjut dari demokrasi liberal dengan perekonomian pasarnya.
Sejarah, menurut Fukuyama, telah berakhir dengan kemenangan mutlak ekonomi pasar bebas (fee market economy). Tidak ada alternatif model pembangunan lain kecuali yang berdasarkan ekonomi pasar bebas; dan model ini yang akan mampu menyelesaikan persoalan pembangunan global. Tetapi, sekali lagi, harapan ternyata tinggal harapan karena apa yang dibayangkan semula ternyata daam perjalanannya tidak terwujud dalam kenyataan.
Memasuki abad 21 hingga dewasa ini, gagasan dan praktik pembangunan global ternyata tetap mereproduksi permasalahan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Sejarah (kemiskinan, keterbelakangn dan ketidakadilan) ternyata belum berakhir.
Memang ada kemajuan yang telah dicapai, tetapi permasalahan pembangunan global tersebut tampaknya tetap dan akan semakin sulit diatasi. Sebab persoalan yang dihadapi itu adalah melekat atau inheren dalam diri paradigmanya. Bahkan berbagai hasil kemajuan yang telah dicapai justru melahirkan berbagai dampak atau masalah-masalah baru yang tidak diperkirakan sebelumnya (unintended). Salah satu di antaranya adalah fenomena degradasi ekologi yang dewasa ini berlangsung semakin parah dan mengglobal.
Maka hingga dewasa ini kita masih mendapati lebih dari 1 milyar orang dari sekitar 7 milyar manusia penghuni Bumi terbelenggu kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Inilah ‘anak haram’ pembangunan, yang secara keseluruhan membentuk kesenjangan struktural atas dasar pembelahan kaya dan miskin dan/atau maju dan terbelakang; yang hal itu tidak saja merupakan kenyataan pahit yang dialami masyarakat dalam suatu negara (elit dan rakyat), tetapi juga antara negara (negara kaya dan negara miskin).
Indonesia di Persimpangan Jalan
Kombinasi antara dinamika persaingan kekuatan global yang mengarah pada bentuk multipolar dan praktik pembangunan global yang melahirkan berbagai permasalah baru yang lebih rumit dan komplek tersebut semakin memicu lahirnya berbagai ‘ketidakpastian’ tentang masa depan global. Semuanya ini dibarengi oleh kemajuan pesat teknologi informasi (IT) sehingga pada ujungnya menghadapkan masyarakat global pada kondisi-kondisi baru, yaitu pengalaman sehari-hari yang terus menerus atas berbagai resiko kehidupan multidimensi yang sulit diperkirakan dan diduga sebelumnya, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkannya.
Inilah yang oleh para teoritisi sosial sering disebut sebagai masyarakat berisiko, ‘risk society’. Kondisi-kondisi yang penuh dengan berbagi resiko kehidupan ini, tentu saja, tidak bisa dihadapi dengan ‘pendekatan konvensional’, termasuk menggunakan cara-cara yang mengandalkan institusi lama, seperti negara, pemerintah atau institusi politik lainnya dalam pengertian biasa (as usual).
Sebaliknya, dibutuhkan pendekatan baru yang melampaui cara-cara lama, dengan mengintegrasikan secara lebih luas dan dalam para pihak yang menghadapi risiko-risiko kehidupan itu. Intervensi dan keterlibatan institusi lama (politik) tidak lagi cukup; dibutuhkan keterlibatan gerakan sub-politik, gerakan pada tataran masyarakat.
Sementara dari segi gagasan dan praktik pembangunan, Indonesia juga bergelut dengan masalah ‘laten’ yang sama dengan yang dialami oleh masyarakat global, khususnya mereka yang tinggal di negara-negara berkembang. Meskipun berbagi upaya kerja keras telah dilakukan selama ini, tetapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan masih menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari kehidupan masyarakat di berbagai tempat.
Harapan besar bahwa praktik pembangunan akan mampu mengatasi secara signifikan masalah kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan, ternyata masih seperti ‘jauh panggang dari api’. Ini suatu keadaan yang bisa difahami melihat pengalaman banyak negara berkembang lainnya yang terlalu percaya pada mitos ‘kebenaran universal’ dibalik gagasan ekonomi pasar bebas (free market economy) yang melandasi praktik pembangunan.
Kepercayaan yang terlalu berlebihan itu telah menyumbat berbagai pikiran kritis yang melihat adanya berbagai kelemahan dasar sistem ekonomi pasar tersebut. Kondisi ini pada gilirannya menghalang-halangi berkembangnya pemikiran alternatif pembangunan yang dinilai berpotensi lebih mampu mengatasi permasalahan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan.
Bagaimanapun, masalah kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan, secara teoritis, adalah problem dasar yang inheren dalam model pembangunan yang bertumpu pada sistem ekonomi pasar bebas. Sehingga fenomena kemsikinan, keterbelakangan dan ketidakadilan tidak lain adalah konsekuensi logis dari model pembangunan konvensional tersebut.
Proses pembangunan yang mereproduksi permasalahan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan itu pada ujungnya berpotensi menggerogoti dan merusak ‘semen sosial’ yang menjadi faktor perekat integrasi sosial. Lalu dibarengi dengan semakin tumbuh suburnya konflik multidimensi maka potensi meluasnya ‘social distrust’ menjadi sulit dibendung, yang hasil akhirnya hampir bisa dipastikan melahirkan disintegrasi sosial dalam masyarakat. Jadi proses pembangunan semacam ini alih-alih pembangunan mengitegrasikan masyarakat (dan bangsa), tetapi sebaliknya justru pembangunan merusak dan menghancurkan sistem sosial yang ada.
Inilah potensi ancaman paling serius, yang mungkin kurang atau bahkan tidak disadari, terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa, dan bahkan negara Republik Indonesia. Pendeknya, ancaman paling berat bukan datang dari faktor eksternal, tetapi berasal dari kondisi internal, yaitu dampak dari cara atau metode yang diadopsi dalam membangun diri sebagai masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu pilihan-pilihan terhadap paradigma pembangunan menentukan nasib masyarakat dan bangsa ke depan.
Oleh karena itu tidak salah kalau sistem kepolitikan yang berkembang dewasa ini tidak ubahnya seperti sistem ekonomi pasar yang mengejar tujuan-tujuan ekonomisme. Kondisi ini jelas melahirkan praktik demokrasi yang parasitik, yaitu berkembangnya politik oligarki yang mempersempit pilihan-pilihan politik rakyat. Bagaimanapun, oligarki politik, yang berakarkan pada cronyism, familyism, dan kekuatan kapital, pada dasarnya adalah sebuah ironi dalam alam demokrasi. Sebab ia menutup pintu rapat-rapat bagi keterlibatan rakyat yang tidak memiliki tiga akar oligarki tersebut.
Dalam dinamika politik semacam ini maka masuk akal kalau partai-partai politik mereproduksi watak pasar yang mentransaksikan semua potensi kekuasaan, akses, dan privilege politik yang melekat pada dirinya. Partai politik lantas mewujud seperti korporasi yang mentraksaksikan setiap eleman politik yang ada dalam sistem kenegaraan, kepemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini jelas mempengaruhi arah perjalanan kenegaraan, kepemerintahan dan kemasyarakatan kita. Melalui proses seperti ini, masyarakat Indonesia telah diposisikan sekedar menjadi market society dan bukannya civil society; masyarakat lebih dipandang sebagai obyek dan bukannya subyek dari pembangunan.
Memaknai Harapan
Kondisi-kondisi di atas tak pelak merupakan wujud dari pengingkaran terhadap cita-cita bapak pendiri bangsa (founding fathers), tentang pembangunan masyarakat bangsa ke depan. Hal ini mengacu pada gagasan bapak pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi ekonomi dan politik, atau menurut konsep Bung Karno tentang sosio-demokrasi. Pengingkaran terhadap cita-cita bapak pendiri bangsa diyakini hanya akan menjerumuskan masa depan rakyat ke arah ‘jalan kegelapan’.
Sebagaimana pernah diingatkan oleh Bung Hatta dalam salah satu tulisannya berjudul “Politik dan Ekonomi” (pertama kali dimuat dalam Daulat Ra’yat, No. 36 Tanggal 10 September 1932): ”Politik dan ekonomi harus sejalan, mendorong ke muka! Politik harus berusaha menuntut hak rakyat. Ekonomi berusaha untuk memperbaiki dan menyelamatkan penghidupan rakyat… memerdekakan penghidupan rakyat”.
Untuk menghindari terjerumus pada jalan kegelapan yang lebih panjang maka diperlukan keberanian untuk putar haluan, ‘banting stir’, mengarahkan kembali perjalananan pembangunan sesuai dengan jalan yang dicita-citakan Para Bapak Pendiri Bangsa. Kita sadari bersama bahwa upaya dan tindakan memutar haluan itu tidak mudah, tetapi langkah itu niscaya akan menuntun kita, bangsa Indonesia, keluar dari jalan kegelapan.