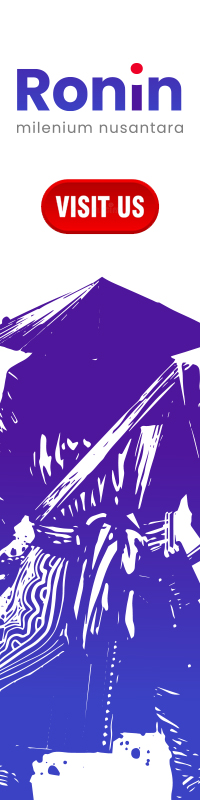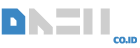Oleh Hasan Ashari
(Mahasiswa Program Doktoral Perbanas Institute)
Indonesia sedang hidup di paradoks likuiditas. Di satu sisi, hasil Financial Sector Assessment Program (FSAP) IMF 2025 menunjukkan sistem perbankan nasional sangat kuat—rasio modal inti bank (CET1) mencapai 23 persen dan rasio likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) menembus 210 persen, jauh di atas standar Basel III. Artinya, bank-bank di Indonesia secara teoritis penuh modal dan uang tunai. Namun di sisi lain, sektor riil di tahun 2025 masih menjerit kesulitan pembiayaan, dunia usaha melambat, dan belanja pemerintah belum sepenuhnya menjadi mesin penggerak ekonomi.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis perbankan. Ia menyingkap kenyataan tahun 2025 bahwa uang di Indonesia ada, tetapi tidak bergerak secara produktif. Dana pemerintah pusat “pernah” menumpuk di Bank Indonesia, dana pemerintah daerah “ditengarai” mengendap di perbankan, sementara bank-bank besar justru mengalirkan likuiditasnya kembali ke Surat Berharga Negara (SBN). Uang berputar di antara entitas negara, pemerintah, bank, dan otoritas moneter, menciptakan circular liquidity yang nyaris tidak menyentuh ekonomi rakyat.
Pelajaran 2025: Negara Menyimpan, Daerah (Bencana) Menunggu
Dalam rapat pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri, 20 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai sekitar Rp234 triliun hingga kuartal III-2025. Angka ini selaras dengan data Bank Indonesia yang menunjukkan dana pemda menganggur masih berada di kisaran Rp200 triliun. Dana yang seharusnya beredar untuk mempercepat pembangunan daerah dan menjaga daya beli masyarakat justru berhenti di rekening bank.
Situasi ini memperlihatkan satu ironi besar: negara memiliki uang, tetapi mekanisme penggerakannya lambat. Pemerintah pusat harus menarik kembali atau merealokasi anggaran dari kementerian/lembaga yang realisasinya rendah, sementara daerah menunggu kepastian anggaran untuk bertindak. Efek gandanya pun hilang. Proyek tertunda, pemulihan ekonomi lokal berjalan lambat, dan likuiditas yang seharusnya mengalir ke bawah kembali terperangkap di atas.
Adanya bencana alam besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, banjir bandang, longsor, dan kerusakan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada paruh akhir 2025, telah memberikan pelajaran berharga, dan menuntut pemerintah dan perbankan agar merespon, segera menyalurkan dana pemerintah dan/atau likuiditas perbankan, di antaranya untuk perbaikan jalan rusak, jembatan terputus, aktivitas UMKM yang lumpuh, dan ribuan keluarga yang kehilangan sumber penghidupan. Akan sangat Ironis, jika di saat kebutuhan belanja/likuiditas sebagai dana pemulihan yang mendesak, ternyata dana/likuiditas masih tersebar dan mengendap, baik di kas daerah maupun dalam struktur anggaran Kementerian/lembaga serta likuiditas perbankan.
Sovereign–Bank Nexus dan Likuiditas yang Berputar di Tempat
Temuan FSAP IMF 2025 mengungkap bahwa sekitar 23 persen aset perbankan Indonesia berbentuk obligasi pemerintah. Hampir seperempat dana bank “dipinjamkan” kembali kepada negara melalui SBN. Hubungan erat ini—dikenal sebagai sovereign–bank nexus—tampak aman dalam jangka pendek. Negara memperoleh pembiayaan murah, bank mendapatkan imbal hasil nyaris tanpa risiko.
Namun secara struktural, pola ini menumpulkan fungsi utama perbankan. Ketika bank lebih nyaman membeli SBN ketimbang membiayai pemulihan usaha pascabencana, industri kecil di daerah, atau UMKM yang terdampak krisis, maka denyut ekonomi riil melemah. Lebih jauh, ketergantungan ini menciptakan loop risiko baru: stabilitas bank menjadi sangat bergantung pada kesehatan fiskal negara.
Paradoks Bank BUMN dan Kredit yang Seret
Bank-bank BUMN yang menguasai sekitar 60 persen aset perbankan nasional berperan sebagai contagion hubs—penyangga utama stabilitas sistem. Namun dalam praktiknya, peran intermediasi mereka justru melemah. Kredit tumbuh terbatas, sementara penempatan dana di SBN dan pasar antarbank meningkat.
Paradoks ini terasa paling nyata di level mikro, khususnya pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di atas kertas, KUR dirancang sebagai kredit inklusif yang dijamin negara. Namun di lapangan, banyak pengajuan KUR di bawah Rp100 juta masih dimintai agunan oleh bank. Bagi pelaku UMKM kecil—terutama yang terdampak bencana di Sumatera—jika syarat ini masih diberlakukan pasti akan menjadi penghalang utama apabila tidak segera dikoreksi oleh perbankan. Usaha sudah terpukul, aset rusak atau hilang, tidak ada yang bisa dijadikan agunan, tetapi akses kredit tetap terkunci oleh logika kehati-hatian perbankan.
Akibatnya, likuiditas perbankan yang berlimpah tidak menjelma menjadi modal kerja bagi pedagang yang tempat usahanya rusak/hilang, petani yang lahannya terendam, atau pengusaha kecil yang perlu bangkit pascabencana. Inilah wajah nyata liquidity trap Indonesia yang perlu “disingkirkan”: uang ada, bank aman, tetapi ekonomi rakyat tertahan.
Refleksi: Ketahanan Tanpa Keberanian
IMF di tahun 2025 menyimpulkan sistem keuangan Indonesia “kuat tapi terkonsentrasi.” Ketahanan ini penting, tetapi tidak cukup. Dalam konteks 2025—ketika bencana alam menuntut belanja cepat, adanya kementerian/lembaga mengembalikan anggaran karena serapan rendah, dan UMKM masih ada yang kesulitan kredit— ternyata masalah utama kita bukan kekurangan uang, melainkan kekurangan keberanian institusional untuk menggerakkannya.
Kunci dari Purbaya Effect bukan sekadar menjaga likuiditas atau menata fiskal secara disiplin, tetapi membangun keberanian kolektif: keberanian pemerintah untuk memastikan APBN/APBD tidak mengendap di birokrasi,
Keberanian bank untuk menyalurkan kredit produktif tanpa membebani UMKM dengan agunan berlebihan, dan keberanian sistem keuangan untuk berpihak pada pemulihan ekonomi riil—terutama saat krisis dan bencana. Dengan itu maka fungsi intermediasi akan hidup kembali.
Refleksi Kebijakan Makroprudensial: Apa yang Perlu Dilakukan?
IMF menyimpulkan bahwa sistem keuangan Indonesia kuat tapi terkonsentrasi, artinya “tahan” namun “tidak efisien” dalam penyaluran kredit. Padahal untuk menggerakkan ekonomi riil, perlu ada kebijakan makroprudensial yang tidak hanya menjaga stabilitas finansial, tetapi juga memperkuat fungsi intermediasi kredit.
Sesuai uraian di atas, pemerintah perlu melakukan kebijakan: memperluas skema jaminan kredit produktif, khususnya bagi UMKM melalui lembaga seperti LPEI dan Jamkrindo/Askrindo, memberikan insentif suku bunga dan pajak, mengurangi beban bunga kredit/memberikan insentif pajak bagi kredit investasi produktif, memberikan kelonggaran kebijakan makroprudensial dan Loan To Value (LTV), melakukan program Literasi Keuangan Produktif, dan memberikan Skema Pembiayaan Hijau dan ESG-Linked Lending untuk mendorong pembiayaan sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
Terakhir, ketahanan sejati bukanlah “saldo yang mengendap” di rekening atau “rasio yang indah” di laporan, melainkan kemampuan sistem keuangan mengalirkan darah ke tubuh ekonomi, termasuk kawasan bencana dan UMKM demi kehidupan jutaan orang. “Purbaya Effect” bukan sekadar menjaga likuiditas atau fiskal yang kuat, tetapi menciptakan keberanian struktural baik di sisi permintaan maupun penawaran kredit. Dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan insentif sektor riil, fungsi intermediasi perbankan bisa hidup kembali, dan kelebihan likuiditas akhirnya menjadi energi penggerak ekonomi riil. Selamat tinggal paradoks!