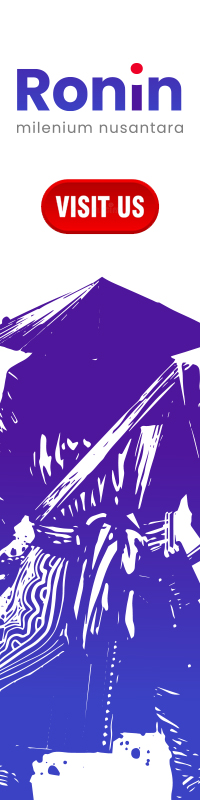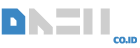JAKARTA, Fenomena hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau yang dikenal sebagai kumpul kebo semakin marak terjadi di kalangan pasangan muda di Indonesia. Pergeseran pandangan terhadap pernikahan disebut menjadi salah satu alasan utama di balik fenomena ini.
Menurut laporan The Conversation, sebagian anak muda memandang pernikahan sebagai hal yang normatif dan penuh aturan rumit. Sebagai gantinya, mereka melihat kohabitasi atau kumpul kebo sebagai hubungan yang lebih murni dan autentik.
Di Asia, termasuk Indonesia, kumpul kebo masih dianggap tabu karena bertentangan dengan budaya, tradisi, dan agama. Namun, studi tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kohabitasi lebih sering terjadi di wilayah Timur Indonesia, terutama di Manado, Sulawesi Utara, yang mayoritas penduduknya non-Muslim.
Menurut peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yulinda Nurul Aini, ada tiga alasan utama pasangan di Manado memilih kohabitasi, beban finansial, prosedur perceraian yang rumit, penerimaan sosial yang lebih tinggi.
“Hasil analisis terhadap data Pendataan Keluarga 2021 (PK21) menunjukkan bahwa 0,6% penduduk Kota Manado melakukan kohabitasi,” ungkap Yulinda.
Dari data PK21, Yulinda menemukan karakteristik pasangan kohabitasi sebagai berikut; 1,9% di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia di bawah 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, sementara 53,5% bekerja di sektor informal.
Kumpul kebo tidak hanya menimbulkan risiko sosial, tetapi juga berdampak negatif bagi perempuan dan anak. Dari segi ekonomi, kohabitasi tidak memberikan jaminan keamanan finansial bagi ibu dan anak karena tidak ada kewajiban hukum bagi ayah untuk memberikan nafkah.
“Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada regulasi yang mengatur pembagian aset, hak waris, atau hak asuh anak,” jelas Yulinda.
Dari sisi kesehatan, kohabitasi berpotensi menurunkan kepuasan hidup dan memicu masalah kesehatan mental akibat minimnya komitmen dan ketidakpastian hubungan.
Data PK21 menunjukkan 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik ringan seperti tegur sapa, 0,62% mengalami konflik serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, 0,26% mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, dan emosional. “Anak-anak sering menghadapi stigma dan diskriminasi terkait status mereka, yang dapat memengaruhi perkembangan identitas dan emosional,” pungkas Yulinda.