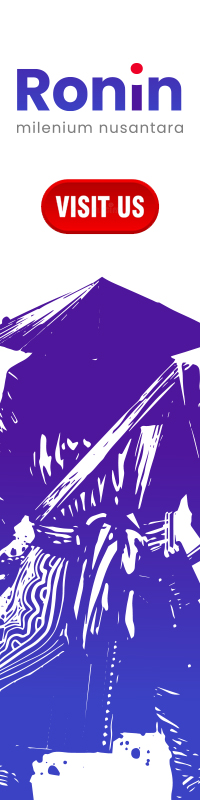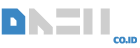Oleh: M. Nur Fadillah, Mahasiswa FISIP Universitas Yuppentek Indonesia (UYI)
Gelombang unjuk rasa yang merebak di berbagai daerah akhir-akhir ini memberi sinyal kuat bahwa demokrasi kita sedang diuji. Alih-alih membuka ruang dialog, respons negara lebih banyak ditandai dengan tindakan represif.
Aparat keamanan tampak sibuk membangun “cipta kondisi”: menciptakan narasi seolah-olah demonstrasi adalah ancaman, aksi massa adalah benih kekacauan.
Langkah pengalihan ini hadir dalam bentuk sekolah yang diliburkan, akses informasi yang dipersempit, jalan ditutup, hingga imbauan agar masyarakat menjaga lingkungannya.
Semua itu memberi kesan bahwa negara berada dalam situasi genting. Padahal, ini lebih menyerupai strategi sistematis untuk menekan kebebasan sipil dan menumbuhkan rasa takut di tengah masyarakat.
Yang paling tragis dari praktik cipta kondisi adalah ketika rakyat sendiri menjadi korban. Peristiwa di Jakarta mencatat nama Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang meninggal setelah tertabrak dan dilindas mobil taktis Barracuda Brimob.
Affan bukan provokator. Ia bukan perusuh. Namun nyawanya melayang di tengah situasi ricuh yang seharusnya bisa dihindari.
Kekerasan serupa juga merambah ruang akademik. Di Bandung, mahasiswa UNISBA dan UNPAS menjadi sasaran gas air mata bahkan oleh unsur militer.
Kampus, yang semestinya menjadi ruang aman bagi dialektika intelektual, justru diperlakukan sebagai medan operasi keamanan.
Krisis politik jalanan ini tidak bisa dipisahkan dari proses legislasi yang berlangsung di parlemen. Banyak kebijakan yang menimbulkan keresahan publik justru lahir dari proses politik yang eksklusif.
Menurut ilmuwan politik, proses legislasi saat ini disebut dengan istilah legislative capture, yakni proses legislasi yang hanya melayani segelintir orang atau kelompok, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks seperti itu, aspirasi rakyat yang disalurkan lewat jalur formal sering menemui jalan buntu. Tidak mengherankan bila masyarakat akhirnya memilih jalan demonstrasi.
Tentu saja, tindakan anarkis dari sebagian massa aksi, perusakan fasilitas umum atau penyerangan aparat, tidak bisa dibenarkan.
Tetapi menyamaratakan seluruh demonstrasi sebagai ancaman negara juga merupakan kesalahan fatal. Kekacauan yang terjadi bahkan berpotensi disusupi provokator yang justru memberi legitimasi pada tindakan represif aparat.
Pertanyaannya kini: sampai kapan kita terus diam? Rakyat yang menyuarakan kekecewaan, baik di jalanan, di kampus, maupun di ruang digital, bukanlah musuh negara. Mereka adalah pemilik sah republik ini, yang sedang menagih janji konstitusi: negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.