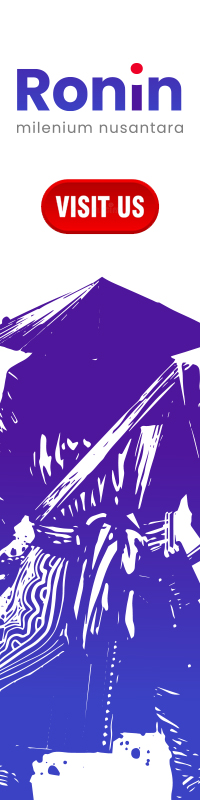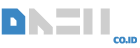Oleh: Hasan Ashari
Mahasiswa Program Doktoral, Perbanas Institute
Sejak otonomi fiskal diberlakukan pasca-reformasi, pemerintah pusat setiap tahun menyalurkan ratusan triliun rupiah ke daerah melalui skema Transfer Keuangan ke Daerah (TKD). Tahun 2026, anggarannya disepakati sebesar Rp693 triliun, naik dari usulan awal Rp650 triliun. Namun, di balik angka besar ini, perdebatan muncul: apakah TKD benar-benar mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah, atau justru menjadi ladang moral hazard bagi pemerintah daerah?
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sempat melayangkan keberatan terhadap rencana penurunan porsi TKD hingga 24,7% dibanding tahun sebelumnya. Para gubernur berargumen bahwa pemangkasan akan menghambat pembangunan. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peningkatan kualitas belanja daerah harus menjadi prioritas. TKD bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Melalui instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa, daerah diharapkan mampu mengelola pembangunan sesuai kebutuhan lokal.
Menurut Kementerian Keuangan, porsi TKD mencapai 25,4% dari APBN 2025 (Rp3.621 triliun) dan 18,3% dari APBN 2026 (Rp3.786,5 triliun). Artinya, hampir seperempat belanja nasional masih ditopang oleh transfer fiskal ke daerah. Bagi banyak daerah, dana ini adalah “urat nadi” pembangunan: dari jalan desa hingga puskesmas, dari sekolah hingga jaringan air bersih.
Namun, di balik kontribusinya terhadap pemerataan, TKD juga menumbuhkan ketergantungan fiskal akut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat rata-rata 56% pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pusat. Artinya, sebagian besar daerah belum mandiri secara fiskal. Alih-alih memacu inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), banyak kepala daerah yang nyaman bergantung pada aliran dana dari pusat.
Dilema Antara Pembangunan dan Moral Hazard
Moral hazard muncul ketika pemerintah daerah tidak menanggung risiko atas perilakunya, tetapi tetap menikmati manfaat dari transfer pusat. Setidaknya ada tiga bentuk moral hazard yang menonjol:
- Moral hazard fiskal – daerah tidak berupaya menggali PAD karena merasa “dijamin” setiap tahun oleh transfer pusat.
- Moral hazard politik – dana transfer dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral, misalnya proyek populis menjelang pilkada.
- Moral hazard birokratik – dana TKD disalahgunakan melalui mark-up, pengadaan fiktif, hingga pungli dalam pencairan.
Masalah ini bukan sekadar asumsi. Data empiris menunjukkan gejala serius. Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkap pada Mei 2025 bahwa sejak 2024 hingga pertengahan 2025, KPK telah menjerat 363 legislator, 171 bupati/wali kota, dan 30 gubernur dalam kasus korupsi — sebagian besar terkait pengelolaan keuangan daerah dan dana transfer dari pusat (DetikNews, 2025).
Angka ini bukan hanya statistik, melainkan potret nyata kebocoran sistemik dalam desentralisasi fiskal. Setiap rupiah yang bocor berarti pelayanan publik yang tertunda, infrastruktur yang mangkrak, dan kepercayaan publik yang terkikis.
TKD: Mesin Pembangunan atau Instrumen Politik?
Secara teori, TKD berfungsi sebagai equalization grant, yaitu mekanisme pemerataan fiskal antarwilayah. Tetapi dalam praktiknya, sering kali tujuan ini kabur di tengah kepentingan politik dan lemahnya tata kelola. Misalnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) kerap diarahkan ke daerah-daerah dengan kepentingan politik tertentu, sementara Dana Desa dalam beberapa kasus menjadi alat konsolidasi kekuasaan lokal.
Kebocoran TKD berdampak langsung pada capaian pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan justru terhenti di meja birokrasi atau diselewengkan lewat proyek fiktif. Akibatnya, kesenjangan antarwilayah tetap tinggi, dan daerah miskin semakin tertinggal karena dana pembangunan tidak sampai ke sasaran.
Kondisi ini menimbulkan paradoks: desentralisasi yang dimaksudkan untuk pemerataan malah berisiko menjadi “desentralisasi korupsi.” Jika tidak dikoreksi, hal ini akan merusak legitimasi pemerintah daerah dan menurunkan efektivitas kebijakan fiskal nasional.
Langkah Korektif: Dari Akuntabilitas ke Reformasi Struktural
Pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan berbagai mekanisme koreksi. Dalam jumpa pers RAPBN 2026, Menteri Purbaya menegaskan bahwa meski total TKD tidak dikurangi, penggunaannya harus dikelola dengan disiplin fiskal dan tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan nasional. Pernyataan ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan di tingkat daerah menjadi keharusan, bukan pilihan.
Ada tiga langkah reformatif yang perlu segera dilakukan:
- Transparansi dan pengawasan publik.
Daerah wajib membuka laporan realisasi TKD secara daring dan mudah diakses publik. Social audit atau pengawasan berbasis masyarakat harus dilembagakan agar kontrol sosial berjalan efektif. - Insentif berbasis kinerja nyata.
Pemerintah dapat memperluas skema Dana Insentif Daerah (DID) dengan indikator berbasis hasil (outcome), seperti peningkatan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan, atau efisiensi belanja, bukan sekadar serapan anggaran. - Digitalisasi dan penguatan SDM.
Banyak penyimpangan terjadi karena lemahnya sistem administrasi. Implementasi e-budgeting, e-audit, dan integrasi data keuangan antara pusat dan daerah akan menutup celah manipulasi. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur wajib menjadi prioritas.
Langkah-langkah ini membutuhkan komitmen politik dan dukungan masyarakat. KPK, BPK, dan BPKP perlu bersinergi dalam pengawasan, sementara masyarakat sipil harus terus menuntut keterbukaan informasi publik.
Penutup: Desentralisasi dengan Integritas
Transfer Keuangan ke Daerah sejatinya adalah wujud keadilan fiskal — agar setiap daerah, kaya atau miskin, mendapat peluang yang sama untuk tumbuh. Namun, keadilan itu hanya akan bermakna jika dana yang ditransfer benar-benar digunakan untuk rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pejabat.
Desentralisasi sejati bukan sekadar memindahkan uang, tetapi juga memindahkan tanggung jawab moral. Ketika setiap rupiah TKD dikelola dengan jujur dan efisien, maka ia menjadi instrumen pemerataan yang sesungguhnya. Tetapi bila disalahgunakan, TKD justru berubah menjadi instrumen ketidakadilan baru yang memperdalam jurang sosial.
Sudah saatnya pemerintah daerah membuktikan bahwa mereka tidak hanya pandai menuntut dana, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkannya. Money should follow integrity — bukan sekadar fungsi.