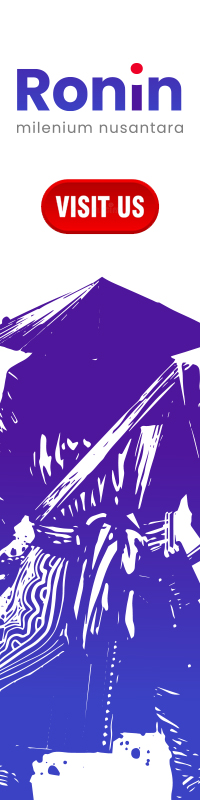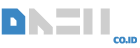Oleh: Eko Sulistyo (Sejarawan dan Deputi di Kantor Staf Presiden (2015-2019).
Soekarno adalah warisan terbesar Abad XX. Dia lahir, kemudian merintis jalan sebagai orang besar, hingga menuju kejatuhannya terjadi di abad tersebut. Sewindu terakhir periode kekuasaannya menjadi fase paling bergemuruh dalam sejarah Indonesia modern (1959-1967). Turbulensi politik begitu tinggi, salah satunya ditandai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dengan terbitnya dekrit tersebut, kekuasaan Soekarno menjadi sangat besar, dan berpotensi menjadi otoriter. Namun dengan kekuasaannya yang besar, Soekarno seolah orang “kesepian” dalam dinamika politik saat itu. Praktis dia tidak memiliki kawan diskusi yang seimbang. Mengingat beberapa kawan berdebatnya sejak masa muda, seperti Hatta dan Sjahrir, berada di luar lingkaran kekuasaan.
Sjahrir bahkan dijebloskannya ke penjara, dengan alasan terkait partai yang dipimpinannya, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dianggap terlibat dalam gerakan separatis PRRI/Permesta. Sjahrir ditahan sejak Januari 1962, dan meninggal dalam status sebagai tahanan politik. Soekarno dengan kekuasaan yang masih tersisa, pada pertengahan April 1966 menetapkan Sjahrir sebagai Pahlawan Nasional yang berlaku surut sejak hari meninggalnya, 9 April 1966.
Perjalanan Sjahrir memang penuh ironi. Dia meninggal dalam status tahanan, dari sebuah negeri yang turut didirikannya. Bersama Soekarno dan Hatta, Sjahrir bahu-membahu membangun negeri yang baru bebas dari penjajahan. Mengingat begitu besar peran mereka, ketiganya memperoleh sebutan “triumvirate” Bapak Bangsa, yang posisinya dalam sejarah tak mungkin tergantikan.
Bersimpang Jalan
Namun dalam perjalanan republik selanjutnya, berdasar alasan politik dan kekuasaan, ketiganya kemudian bersimpang jalan. Dimulai dengan Sjahrir, ketika terjadi Clash II pada akhir 1948, posisinya sudah di luar lingkaran elit pemerintahan. Kemudian menyusul Hatta yang mundur sebagai wakil presiden pada pertengahan dekade 1950-an.
Setelah menjadi warga biasa, Hatta sempat menulis risalah “Demokrasi Kita” (1960), sebuah esai yang mengkritik keras sistem Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Hatta antara lain mengatakan, “sejarah dunia memberi petunjuk, bahwa diktatur yang bergantung pada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistem yang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri.”
Dalam pandangan Hatta pula, golongan dan elite politik yang ada di sekitar Soekarno, datang dari berbagai aliran yang sejatinya saling bertentangan satu sama lain. Ikatan di antara mereka hanya bergantung pada keberadaan figur Soekarno. Mereka sekadar setuju saja pada apa yang menjadi kehendak Soekarno.
Tampaknya memang ada perbedaan “imajinasi” antara Hatta dan Soekarno soal keindonesiaan sehingga keduanya harus berpisah jalan. Soal konsep Demokrasi Terpimpin, hal itu tidak bisa dipisahkan dari hasrat Soekarno sejak masa muda tentang penyatuan tiga kekuatan politik “Nasakom” serta perlunya sebuah partai pelopor yang monolitik.
Soekarno tidak tertarik pada demokrasi model Barat yang multi-partai. Itu sebabnya Soekarno sempat melakukan eksperimen soal partai tunggal, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 27 Agustus 1945. Namun usianya tidak sampai seminggu karena muncul kekhawatiran soal kemungkinan tumpang tindih antara PNI dan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).
Hari-hari pasca terbitnya Dekrit, Soekarno praktis tinggal sendiri di “menara gading” kekuasaan. Setidaknya ada dua tokoh yang masih secara intensif berhubungan dengan dirinya terkait kedinasan atau politik, yaitu Jenderal Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Perdana Menteri Djuanda. Mengingat beberapa tokoh lainnya dengan berbagai alasan “dikarantina politik” oleh rezim Soekarno, seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mochtar Lubis, dan lain-lain.
Seberapa pun tingginya jabatan, kedua nama yang disebut terakhir, dalam aspek gagasan tidak dapat menggantikan posisi Sjahrir dan Hatta. Nasution dan Djuanda bukanlah teman diskusi yang setara bagi Soekarno. Djuanda adalah seorang proto teknokrat yang pernah ada sebelum munculnya nama-nama seperti Widjojo Nitisastro atau Ali Wardana.
Demikian dengan Nasution. Hubungan Soekarno dan Nasution semata-mata politis, masing-masing berkepentingan dalam menjaga kontinuitas kekuasaan. Beberapa kali usul Nasution pernah ditolak oleh Soekarno. Salah satunya saat mencalonkan Mayjen TNI Gatot Soebroto sebagai KSAD untuk menggantikannya.
Sementara Djuanda, sejak masih berstatus mahasiswa “Technische Hoogeschool te Bandoeng” atau ITB sekarang, hingga menjadi menteri, dikenal sebagai figur a-politis. Sulit membayangkan terjadi perdebatan bermuatan ideologis antara Djuanda dan Soekarno. Apa yang ada dalam pikiran Djuanda, kurang lebih adalah “kerja, kerja dan kerja”.
Akhir Kisah Kekuasaan
Setelah kematian Djuanda, pada November 1963, posisi Djuanda digantikan oleh Soebandrio yang menjabat Menteri Luar Negeri. Dibanding pendahulunya, Soebandrio lebih politis tapi dari segi gagasan tetap saja tidak dapat mengimbangi Soekarno. Soebandrio lebih memikirkan mengamankan kekuasaannya sendiri.
Situasi yang hampir mirip terjadi pada pengganti Nasution selaku KSAD, yakni Mayjen Ahmad Yani. Dalam aspek gagasan, level Yani masih di bawah Nasution, mengingat Yani lebih sebagai tipikal perwira lapangan. Oleh sebab itu, Yani harus mencari ruang lain agar bisa masuk dalam lingkaran pertama Soekarno.
Mencari ruang kesesuaian antara Yani dan Soekarno tidaklah sulit. Keduanya dikenal sebagai figur flamboyan, dan sangat menikmati kehidupan. Beda dengan Nasution, yang lebih puritan. Mungkinkah sebuah kebetulan, kesesuaian hubungan antara Soekarno dan Yani, meski dengan cara yang berbeda, menjadikan nasib mereka juga mirip, sirna dari panggung sejarah pasca Peristiwa 30 September 1965.
Demikian akhir kisah kekuasaan Soekarno, berada dalam kesenyapan, jauh dari teman-teman seperjuangannya dalam mencapai Indonesia Merdeka. Praktis tidak ada lagi perdebatan dan adu gagasan tentang arah perjuangan bangsa diantara mereka. Kekuasaan sudah menjadi monolitik, perbedaan dalam pandangan politik dianggap seteru politik.
Politik kekuasaan menjadi sebatas gelora dan gemuruh saling adu kekuatan dan pengumpulan massa. Di titik inilah, perlahan kejayaan Soekarno sebagai pemimpin mulai meredup. Pasca Peristiwa 30 September 1965, Soekarno harus meninggalkan istana dengan segala atribut kebesaran, kenangan, dan koleksi benda-benda seni kesayangannya.