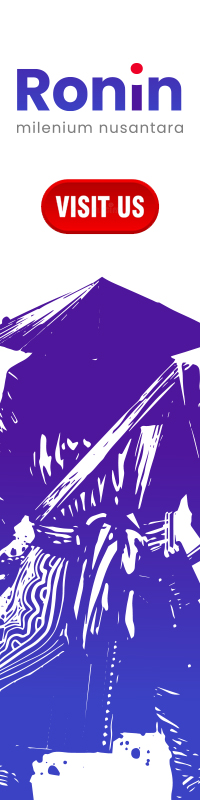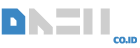JAKARTA, Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Polri semakin memanas setelah penunjukan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembahasan yang tertunda sejak masa jabatan Presiden Joko Widodo. Pada 13 Februari 2025, surat presiden (surpres) mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi UU Polri dibubuhi tanda tangan Prabowo, memicu kekhawatiran baru terkait potensi perpanjangan kewenangan Polri.
Revisi UU Polri pertama kali dibahas pada akhir masa jabatan Jokowi dan sempat tertunda setelah usulan disetujui oleh DPR RI pada 29 Mei 2024. Pembahasan yang kini dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo berpotensi membuka jalan bagi perluasan kewenangan Polri yang menuai kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil.
Meskipun sudah ada penunjukan oleh pemerintah, pimpinan DPR RI menegaskan bahwa mereka belum menerima surpres terkait revisi UU Polri. Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan bahwa pembahasan revisi UU Polri belum akan dilanjutkan dalam waktu dekat. “Belum ada surpres, kami (akan) lihat lagi,” ungkap Puan kepada awak media pada Kamis (20/3/2025).
Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada rencana pembahasan revisi UU Polri di DPR. Meski begitu, Ketua Kelompok Fraksi Partai Nasdem Komisi III, Rudianto Lallo, menyatakan kesiapan untuk membahas revisi jika dianggap mendesak, dengan prioritas utama pada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dijadwalkan selesai pada Oktober 2025.
Revisi UU Polri mendapat kritik keras, terutama terkait potensi penguatan kewenangan kepolisian yang berisiko mengancam kebebasan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, yang terdiri dari Imparsial, YLBHI, dan berbagai organisasi nonpemerintah, mencatat bahwa naskah revisi UU Polri menambah pasal-pasal yang memperluas kekuasaan Polri, tanpa memperhatikan pentingnya mekanisme pengawasan publik.
Salah satu pasal kontroversial adalah Pasal 16 Ayat 1 Huruf q yang memberikan Polri kewenangan untuk melakukan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan di ruang siber. Pengawasan ini bisa meliputi tindakan pemblokiran atau pemutusan akses internet, yang sebelumnya telah digunakan untuk meredam protes masyarakat, seperti yang terjadi pada 2019 di Papua. Tindakan semacam ini kemudian diputuskan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menilai bahwa perluasan kewenangan Polri dalam revisi ini berpotensi mempersempit ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan pemerintah. “Revisi UU Polri berpotensi mengancam hak dan kebebasan berekspresi masyarakat,” ujar Ardi.
Revisi UU Polri juga memberikan kewenangan baru bagi Polri dalam bidang intelijen. Pasal 16A draf revisi UU Polri memperbolehkan Polri untuk melakukan penggalangan intelijen, yang bisa mencakup tindakan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku sasaran sesuai dengan keinginan pihak yang melakukan penggalangan.
Selain itu, dalam draf revisi UU Polri, Polri juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengawasan ini mencakup pengaruh terhadap tahap rekrutmen penyelidik dan penyidik KPK, yang sebelumnya menjadi tugas independen.
Bambang Rukminto, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mengungkapkan kekhawatirannya tentang potensi disalahgunakannya perluasan kewenangan Polri. “Perluasan kewenangan ini bisa menyebabkan abuse of power dan semakin memperkecil ruang kebebasan masyarakat,” ujar Bambang.
Selain mengancam kebebasan berekspresi, revisi UU Polri yang berfokus pada perluasan kewenangan juga tidak menyentuh masalah-masalah mendasar di dalam tubuh Polri, seperti mekanisme pengawasan yang lemah terhadap tindakan anggota kepolisian. Pengawasan internal Polri, yang selama ini dikelola oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), sering kali dianggap tidak efektif dan lebih mirip lembaga kuasi eksekutif dengan fungsi terbatas.
Dengan perluasan kewenangan yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang jelas, revisi UU Polri berpotensi mengarah pada penciptaan negara kepolisian (police state). Bambang Rukminto menilai bahwa hal ini bisa mengarah pada ancaman terhadap hak asasi manusia (HAM) dan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar negara Indonesia.
“Revisi UU Polri yang ada saat ini tidak menjawab kebutuhan masyarakat, malah berisiko memperbesar kewenangan Polri tanpa sistem kontrol yang kuat,” tambah Bambang.
Di tengah gelombang protes terhadap revisi UU TNI yang baru saja disahkan, revisi UU Polri berpotensi menghadirkan masalah serupa, terutama terkait dengan pengaruh politik dan kelemahan pengawasan. Sebagai langkah maju, Bambang menyarankan agar pemerintah dan DPR membuka ruang dialog yang lebih besar dengan masyarakat untuk mengevaluasi draf revisi UU Polri sebelum dibawa ke rapat paripurna.
“Yang harus dilakukan adalah membuka ruang dialog dan mengubah draf revisi UU Polri sesuai dengan harapan masyarakat,” tegas Bambang.