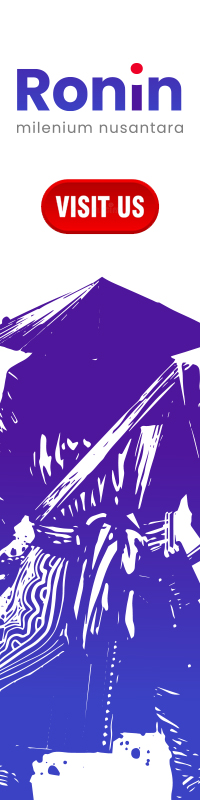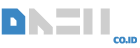Oleh: Hasan Ashari
Mahasiswa Program Doktor Perbanas Institute
Istilah Purbaya Effect sering dipakai untuk merujuk pada klaim terjaganya stabilitas ekonomi Indonesia sepanjang 2025. Di tengah transisi pemerintahan dan ketidakpastian ekonomi global, stabilitas kembali menjadi kata kunci yang paling sering diulang. Pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5 persen tahun 2025, sistem keuangan relatif aman, dan gejolak global diklaim masih bisa diredam. Namun di balik ketenangan itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah efek tersebut benar-benar dirasakan ekonomi riil, atau sekadar “omon-omon” stabilitas yang nyaman di atas kertas?
Namun seperti lazimnya kebijakan publik, kata “stabilitas” tidak pernah bebas dari perdebatan. Apa yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai keberhasilan menjaga fondasi ekonomi, oleh pihak lain justru dibaca sebagai tanda ekonomi yang berjalan di tempat. Polemik pun mengemuka: apakah Purbaya Effect benar-benar nyata, atau sekadar “teori ilmiah” yang menenangkan di tengah kegelisahan publik?
Dalam tulisan ini diketengahkan berbagai pendapat di media massa baik dari kubu yang pro maupun kontra atas hasil kerja Menteri Purbaya sampai dengan Februari 2026 ini. Mulai dari isu pertumbuhan ekonomi sampai dengan indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia.
Argumen Pro: Stabilitas sebagai Benteng di Tengah Tekanan
Dari sisi pendukung, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dipandang sebagai capaian moderat namun rasional dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya, termasuk dalam situasi global yang penuh ketidakpastian—mulai dari ketegangan geopolitik hingga kebijakan suku bunga ketat di negara maju—angka tersebut dinilai mencerminkan daya tahan ekonomi domestik. Pertumbuhan ini tidak dimaknai sebagai puncak, melainkan sebagai dasar yang dijaga agar ekonomi tidak tergelincir lebih dalam.
Kenaikan defisit APBN juga dibaca dalam kerangka kebijakan kontra-siklikal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara memilih memperlebar peran fiskal ketika sektor swasta belum sepenuhnya pulih. Selama berada dalam batas undang-undang dan dikelola secara hati-hati, defisit dianggap sebagai instrumen stabilisasi, bukan tanda kehilangan disiplin fiskal.
Soal daya beli publik yang masih lemah, kelompok pro mengakui adanya tekanan, tetapi melihatnya sebagai fase transisi. Normalisasi harga, perubahan pola konsumsi, dan kehati-hatian pengusaha dan rumah tangga dinilai sebagai bagian dari proses penyesuaian pasca tejadinya guncangan ekonomi global. Optimisme tetap dijaga dengan keyakinan bahwa konsumsi akan pulih seiring membaiknya ekspektasi masyarakat.
Mengenai tekanan terhadap rating utang dan nilai tukar rupiah pun, kubu pro lebih banyak mengaitkan dengan faktor eksternal. Dari sudut pandang ini, fundamental domestik dianggap masih cukup kuat, sementara fluktuasi pasar dinilai lebih mencerminkan sentimen global ketimbang kelemahan struktural perekonomian.
Lalu terkait lemahnya penyaluran kredit perbankan, tidak sepenuhnya merupakan kesalahan sistem keuangan. Kubu pro melihat persoalan utama berada pada sisi permintaan: dunia usaha masih berhati-hati menambah utang di tengah ketidakpastian ekonomi. Kucuran Rp275 triliun kepada Bank Himbara sudah berhasil meningkatkan jumlah uang beredar dan meningkatkan persentase penyaluran kredit perbankan. Demikian pula dengan pelemahan IHSG, yang dianggap sebagai koreksi wajar pasar modal dalam menghadapi risiko global.
Singkatnya, Purbaya Effect dalam kacamata pro bukanlah janji lonjakan ekonomi “simsalabim”, melainkan upaya menjaga ekonomi tetap berdiri—meski lajunya pelan.
Dari Optimisme Teknis ke Skeptisisme Publik
Di titik inilah perdebatan mengemuka. Apa yang dibaca sebagai kehati-hatian “level dewa” yang bersifat teknokratik oleh kubu pro, oleh kelompok kontra justru dipersepsikan sebagai jarak yang makin lebar antara narasi kebijakan dan realitas sehari-hari “rakyat jelata”. Ketika stabilitas dirayakan lewat indikator makro, sementara rumah tangga menahan belanja, penyaluran kredit seret, dan pasar saham merespons dengan koreksi “merah menyala”, optimisme kebijakan mulai dipertanyakan relevansinya.
Perdebatan pun bergeser: bukan lagi sekadar apakah sistem keuangan aman, melainkan apakah rasa aman itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat?
Argumen Kontra: Stabilitas yang Kehilangan Daya Dorong
Bagi kelompok kontra, pertumbuhan ekonomi 5 persen justru mencerminkan stagnasi dan “bukan prestasi.” Angka ini dinilai terlalu rendah untuk menjawab tantangan bonus demografi, penciptaan lapangan kerja, dan tekanan biaya hidup. Stabilitas, dalam konteks ini, berubah menjadi comfort zone—aman bagi negara, tetapi “kurang enak dirasakan” masyarakat.
Kenaikan defisit APBN dipandang sebagai sinyal tekanan fiskal, bukan sekadar strategi. Ketika belanja negara membesar namun dampaknya ke konsumsi dan investasi terasa lemah, defisit berisiko menjadi beban jangka menengah. Masalahnya bukan legalitas bahwa defisit itu sesuai dengan undang-undang, melainkan efektivitasnya bagi rakyat banyak.
Daya beli yang melemah juga tidak lagi dianggap sebagai gejala sementara. Bagi kubu kontra, ini telah menjadi realitas sosial yang menetap. Kelas menengah tertekan, konsumsi defensif, dan optimisme publik menipis. Dalam situasi ini, narasi stabilitas terdengar elitis dan jauh dari pengalaman sehari-hari masyarakat.
Tekanan pada rating utang dan nilai tukar rupiah dibaca sebagai alarm kepercayaan. Investor tidak hanya melihat faktor eksternal, tetapi juga kombinasi pertumbuhan moderat, defisit yang melebar, dan lemahnya konsumsi. Penjelasan bahwa fundamental masih kuat terdengar normatif ketika pelaku pasar bersikap waspada.
Mandeknya kredit perbankan, menurut kelompok kontra, mencerminkan ekonomi yang enggan bergerak. Dunia usaha menahan ekspansi bukan karena kekurangan likuiditas, melainkan karena prospek keuntungan yang belum meyakinkan. Kucuran Rp275 triliun kepada Bank Himbara tidak berefek apa-apa. Pelemahan IHSG pun dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan pasar terhadap prospek jangka menengah.
Dalam pandangan ini, kelompok kontra menganggap Purbaya Effect lebih menyerupai manajemen ekspektasi alih-alih terobosan kebijakan yang efektif.
Stabilitas dan Ujian Legitimasi
Pada akhirnya, polemik Purbaya Effect tidak berhenti pada soal kubu siapa yang benar atau salah. Kubu pro mengingatkan bahwa menjaga sistem keuangan tetap stabil di tengah gonjang-ganjing ekonomi global adalah prasyarat penting. Namun kubu kontra mengajukan pertanyaan yang tak kalah mendasar: stabilitas untuk siapa, jika tidak cukup terasa di iklim usaha, dapur rumah tangga, dan lantai bursa?
Di sinilah kebijakan ekonomi menjadi politis. karena stabilitas yang terlalu lama dipertahankan tanpa naiknya kesejahteraan berisiko kehilangan legitimasi sosial. Ekonomi mungkin tidak jatuh, tetapi publik merasa lelah menanti janji-janji.
Maka pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah Purbaya Effect nyata atau sekadar retorika stabilitas, melainkan apakah stabilitas itu mampu bertransformasi menjadi optimisme kolektif. Sebab dalam politik ekonomi, ukuran keberhasilan bukan hanya grafik dan rasio, melainkan menjaga agar kepercayaan rakyat kepada negara agar selalu ada dan abadi.