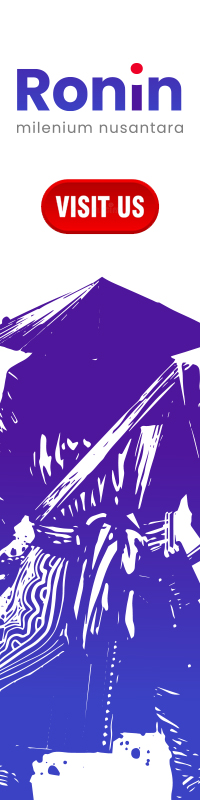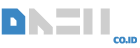Kaum Padri terdiri atas ulama-ulama yang memiliki tujuan untuk memurnikan ajaran Islam di Minangkabau
JAKARTA, Perang Padri merupakan salah satu pertempuran yang dilatarbelakangi oleh perpecahan di kalangan rakyat Minangkabau, tepatnya antara kaum Padri dan kaum Adat.
Pertempuran ini terjadi di daerah Sumatera Barat dan terbagi ke dalam dua periode yang terpisah, yaitu pada tahun 1821-1825 dan 1830-1837.
Mengutip dari buku Explore Sejarah Indonesia yang ditulis oleh Abdurakhman dan Arif Pradono, kaum Padri menilai bahwa kaum Adat telah melakukan praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam.
Sehingga, kaum Padri ingin melakukan pemurnian praktik ajaran Islam dengan memberantas kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang itu.
Kaum Padri terdiri atas ulama-ulama yang memiliki tujuan untuk memurnikan ajaran Islam di Minangkabau, sedangkan kaum Adat merupakan kelompok masyarakat di Minangkabau yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhur mereka.
Pertentangan antara Kaum Padri dan Kaum Adat Dimanfaatkan oleh Belanda
Perang saudara yang terjadi antara kaum Padri dan kaum Adat memberikan Belanda celah untuk mempengaruhi masyarakat Minangkabau.
Maka, pada tahun 1821, Pemerintah Kolonial Belanda yang bernama James Du Puy melakukan perjanjian dengan kaum Adat.
Dari perjanjian tersebut, Belanda berhasil menduduki sejumlah daerah. Akibat dari tindakan kaum Adat dan Belanda, akhirnya terjadilah Perang Padri.
Periode Pertama Perang Padri (1821-1825), Gencarnya Kekuatan Kaum Padri
Di periode yang pertama, kaum Padri menyerang pos-pos Belanda dan melakukan pencegatan terhadap patroli-patroli mereka. Pada September 1821, pos-pos Belanda di Simawang, Soli Air dan Sipinang jadi sasaran penyerangan kaum Padri.
Kala itu, dengan jumlah 20.000-25.000 pasukan, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman menyerang Belanda di hutan sebelah timur Gurun. Pasukan Belanda yang hanya berjumlah 200 orang serdadu Eropa ditambah 10.000 pasukan kaum Adat melakukan perlawanan.
Pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman cukup sulit dikalahkan, hingga akhirnya Belanda memutuskan untuk mengirimkan surat ajakan berdamai. Mengetahui taktik Belanda, Tuanku Pasaman tidak menanggapi ajakan Belanda dan terus menggencarkan perlawanan di berbagai tempat.
Perlawanan Pasukan Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Imam Bonjol
Pada tahun 1822, pasukan dari Tuanku Nan Renceh menyerang Belanda di bawah pimpinan Kapten Goffinet dan meraih kemenangan.
Belanda mulai menduduki daerah IV Koto pada Februari tahun 1824, tindakan ini menyulut kemarahan kaum Padri di Bonjol.
Di bawah komando Peto Syarif atau yang lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol, kaum Padri melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Saruaso.
Memasuki tahun 1825, Belanda kembali mengajukan perjanjian damai. Perjanjian itu berisi bahwa Belanda mengakui kekuasaan tuanku-tuanku di Lintau, IV Koto, Telawas, dan Agam.
Sayangnya, perjanjian tersebut mengecewakan kaum Adat. Mereka menganggap Belanda tidak menepati janji dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri.
Periode Kedua Perang Padri (1830-1837), Kaum Adat Mulai Melakukan Perlawanan
Kaum Adat yang kecewa dengan perjanjian damai mulai menentang dan melawan balik Belanda. Pada periode kedua ini, kaum Padri dan kaum Adat mulai bersatu. Mereka menyadari bahwa musuh yang sebenarnya adalah Belanda.
Dengan kekuatan yang meningkat, kedudukan Belanda di Sumatera Barat semakin terdesak. Bahkan, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengangkat kolonel G.P. Jacob Elout untuk mencegah meluasnya perlawanan dan kekuasaan kaum Padri.
Pada tahun 1832, serangan Belanda kepada kaum Padri semakin gencar. Bahkan, mereka menyerang pos-pos pertahanan kaum Padri yang berada di Banuhampu, Kamang, Guguak Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Candung, dan beberapa lainnya di Agam.
Kekalahan Pasukan Padri
Di tahun 1834, kekuatan Belanda berfokus untuk menguasai wilayah Bonjol. Hingga akhirnya pada tahun 1835, pasukan Padri mengalami kesulitan dan dipukul mundur.
Pada 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaan berunding dengan Belanda. Sayangnya, usaha perundingan itu justru mengalami kegagalan dan memicu terjadinya peperangan lagi.
Benteng Bonjol dikepung dan berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol dan sejumlah pejuang lainnya menyerahkan diri untuk menjamin keselamatan kaum Padri.
Setelah menyerahkan diri, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Ambon, dan akhirnya wafat di Manado pada 6 November 1864.