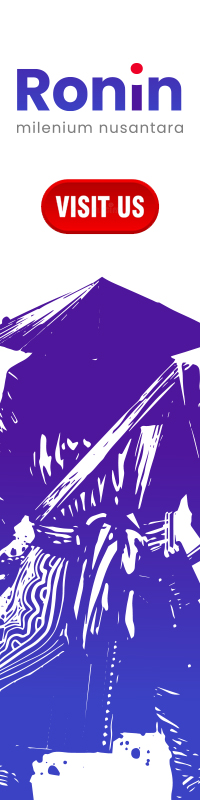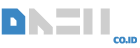Oleh: Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum DPP GMNI 2019-2023, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia
Seorang Indonesianis, Ben Anderson pernah berkata bahwa revolusi Indonesia adalah “revolusi pemuda”. Para pemuda, katanya, selalu memiliki andil dalam konstelasi dan perubahan politik negeri ini. Dan hal ini dibuktikan dalam catatan sejarah, di mana tak ada peristiwa politik penting di negeri ini yang tak melibatkan peran kaum muda.
Mulai dari pembentukan Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, sampai Revolusi Agustus 1945.
Bahkan dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, para pemuda ikut andil dalam peristiwa pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, Reformasi 1998. Artinya konsep pemuda selalu identik dengan perubahan, kebaruan dan kemajuan. Sehingga ia bukan sebuah konsep yang hanya terbatas pada kategori “umur”, namun lebih sebagai sebuah konsep yang bertaut dengan “sikap” dan “mentalitas”.
Namun, apabila kita berbicara tentang politik saat ini, yang hadir di benak kita ialah mengalirnya segelontor dana dan upaya merebut kursi kekuasaan. Sehingga ketika kekuasaan itu mulai dijalankan, ia gaduh dengan pertikaian, terutama soal berebut sumber dana dan kalkulasi kursi kekuasaan.
Kerakusan pun justru dirayakan dan jual beli kekuasaan menjadi ritual tahunan. Demokrasi menjadi semacam “pasar loak” di mana transaksi dan pertukaran antara uang, kekuasaan serta jabatan menjadi habitat yang wajar.
Wajah kekuasaan pun tak lebih semacam “komedi putar”, yang hanya dipenuhi oleh mereka yang pandai berseni peran. Bahkan sirkulasi kekuasaan menjadi semacam permainan “tong setan”, yang hanya menampilkan wajah-wajah politisi yang membosankan (Lu lagi, Lu lagi). Wajah-wajah politisi tua masih saja terus mendominasi panggung politik negeri ini.
Hal ini senada dengan beberapa hasil survei terkini, di mana figur politisi tua masih memiliki popularitas, bahkan elektabilitas yang cukup tinggi. Kemunculan beberapa nama lama seperti Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, Wiranto, Megawati Soekarnoputri, sampai Prabowo Subianto memperlihatkan tokoh-tokoh tua masih sangat dominan dalam dunia perpolitikan kita saat ini.
Artinya, bisa dikatakan dunia politik kita masih didominasi oleh tatanan lama yang nampak tak banyak membawa perubahan, kolot dan mapan. Hal ini membawa politik Indonesia ke dalam masa “menopause”, di mana politik berjalan dalam bayang-bayang kekeroposan, lemahnya “elan vital” perubahan dan cenderung stagnan. Bahkan mungkin “jompo”.
Sehingga politik semacam ini tak bisa diharapkan mampu meraih capaian-capaian yang mengagumkan. Ia telah kehilangan “gerak”, bahkan gerak itu hanya berpindah bergantian di antara sederet kekuasaan lama. Ide-ide perubahan pun tertelan oleh kekuasaan, dan kebaruan pun tercekik, tak berkembang.
Di tengah situasi semacam ini, peran pemuda layaknya dalam catatan sejarah sebagai pembawa perubahan tak kunjung tampil dalam arena politik negeri ini. Bahkan menurut suvei Demos, hanya 49,8 persen anak muda yang mempunyai partisipasi politik yang tinggi. Sementara sisanya, partisipasi politiknya dapat dikatakan cenderung masih rendah.
Artinya, kesadaran dan partisipasi politik kaum muda masihlah sangat lemah. Ia tak lebih hanya menjadi penggembira pada momen-momen pemilihan umum lima tahunan.
Matinya Politik Kaum Muda
Minimnya partisipasi kaum muda bukan tanpa sebab. Partisipasi kaum muda menjadi rendah akibat persoalan, pertama, adanya konsolidasi oligarki kekuasaan ekonomi-politik warisan Orde Baru, yang kemudian menempatkan kaum tua terus berkuasa di posisi puncak partai politik. Hal ini kemudian menciptakan fenomena personal party di mana struktur partai politik berada dalam dominasi tokoh sentral.
Fenomena ini membuat partai politik sekedar “kendaraan” bagi segelintir tokoh partai dan para pemilik modal besar untuk meraih ambisi kekuasaan. Partai politik hanya menjadi perpanjangan tangan segelintir “orang kuat”, baik pemilik partai maupun para pemilik modal. Hal ini hampir melanda semua partai politik di negeri ini.
Corak personal party inilah yang kemudian menutup ruang bagi demokrasi internal partai. Di mana segala kebijakan partai, seperti penentuan kandidat untuk jabatan politik (legislatif dan eksekutif), penentuan komposisi struktural partai sampai kaderisasi harus sesuai kehendak atau harus mendapat “restu” dari tokoh sentral partai.
Kenyataan semacam ini membuat segala mekanisme politik di dalam partai rawan akan politik transaksional yang melibatkan segelintir orang di dalam partai. Sehingga, yang seringkali terjadi adalah proses rekruitmen anggota partai yang hanya berbasis pada kekuatan finansial dan bersifat transaksional.
Hal ini kemudian membuat ruang politik kaum muda semakin kecil untuk berpartisipasi dalam konstelasi dan kepemimpinan politik. Kecuali untuk mereka, kaum muda yang memiliki modal finansial yang cukup banyak.
Seperti yang ditemukan ICW, di mana 44,6 persen anggota DPR yang terpilih pada periode 2009-2014 adalah pengusaha. Latar belakang pengusaha itu menjadi korelasi penting bahwa kekuatan uang kini menjadi penggerak utama dalam mesin politik kita. Bahkan menjadi dasar proses rekruitmen anggota partai politik.
Kedua, adanya personal party ini juga membuat kaderisasi didalam partai hanya sebatas “dinasti politik”. Di mana kaderisasi dan sirkulasi kepemimpinan politik hanya terbatas pada mereka yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh sentral didalam partai.
Hal ini kemudian membuat peluang kaum muda untuk berperan kian menipis. Kecuali untuk mereka kaum muda yang didukung sumber daya warisan dinasti politik. Seperti yang ditemukan oleh Litbang Kompas dimana 13 persen anak muda yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 adalah akibat memiliki tali kekeluargaan dengan elite-elite partai.
Bahkan temuan Obsesion News menyatakan dari 10 anggota DPR RI Periode 2014-2019 peraih suara terbanyak adalah mereka putra mantan Presiden, putra dan putri Ketua Umum parpol, putra dan putri Gubernur, hingga anak mantan Bupati dan tokoh penting didalam partai.Sederet nama-nama politisi muda seperti Puan Maharani, Edhie Baskoro, Dodi Alex Nordin, dan Hanafi Rais adalah sederet nama-nama politisi muda yang akibat pertalian darah, mereka bisa mendapatkan kemudahan memperoleh posisi politik.
Sehingga melihat data ini, kita bisa simpulkan bahwa politik kaum muda yang kini mengemuka adalah politik yang hanya bertujuan meneruskan kiprah dan warisan politik bapak/ibunya yang sedang berkuasa, mantan pejabat tinggi atau sedang menjabat jabatan tinggi sebagai tokoh penting didalam partai.
Dari semua data ini pula kita bisa menyimpulkan, bahwa basis keterlibatan aktif para kawula muda dalam dunia politik saat ini bukanlah karena kapasitas politik, integritas dan kompetensi yang dimilikinya. Namun lebih merupakan akibat kekuatan finansial yang dimilikinya dan mengandalkan politik kekerabatan untuk membangun elektabilitas yang tinggi.
Semua ini membuat politik kaum muda justru tergilas oleh pola pikir dan mentalitas lama. Menjadikan politik kaum muda hanya menjadi bagian dari jejaring patronase kekuasaan lama. Yang artinya, politik kaum muda mati dalam pasungan “politik oligarki” yang sedang berkuasa saat ini.
Maka wajar jika politik kaum muda yang mengemuka saat ini justru tak membawa perubahan apapun. Sejalan dengan survey yang dirilis oleh Lingkaran Survey Indonesia, dimana hanya 24,8 persen responden yang menyatakan bahwa politisi muda saat ini berperilaku baik (Tempo, September 2011). Artinya mayoritas (75,2%) responden masih menilai kualitas politisi muda tidak lebih baik dari politisi yang lebih senior.
Lantas, apa yang harus kita lakukan?
Mencipta Habitus dan Menghidupkan Kembali “Yang Politis”
Kita telah melihat bahwa ternyata politik kaum muda masuk ke dalam krisis politik yang sekarang melanda kita semua yakni sebuah krisis politik yang mengarah pada “hancurnya keadaban (civility) politik”, dimana politik menjadi sekadar sarana untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sebuah upaya dari kekuatan oligarki politik untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik mereka.
Hal ini mengarahkan dunia politik kita ke dalam situasi “banalitas” dimana kejahatan politik seperti politik uang, manipulasi suara, politik transaksional dan klientisme politik menjadi sesuatu yang wajar, seolah-olah masuk akal dan menjadi kerangka yang menstrukturkan tindakan.
Sehingga membentuk apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai “habitus”, sebuah struktur mental yang dibentuk oleh proses internalisasi antara aktor dengan dunia sosial atau kondisi objektif diluar dirinya. Habitus inilah yang kemudian membimbing para aktor dalam mempersepsi, merasakan, berpikir hingga melakukan praktik politik.
Untuk itu jalan yang mungkin untuk mengubah kenyataan politik saat ini ialah dengan mencipta habitus politik baru. Disinilah pemuda dapat memainkan peranan, dimana melalui komunitas politik yang digelutinya, kaum muda aktif membangun nilai-nilai sebagai ukuran tindakan politik.
Mulai dari organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang ada, pemuda haruslah aktif membangun “politik sebagai pikiran”, “politik sebagai perjuangan”. Dimana politik berivisi memperjuangkan mereka yang terusir dari sistem kordinat politik oligarkis, yakni mereka; “rakyat” sebagai tubuh demokrasi yang justru disingkirkan dari demos.
Dengan kata lain, pemuda harus membangun nilai dan visi politik seperti apa yang dikatakan Jacques Rancière yakni politik sebagai upaya memperjuangan mereka; orang-orang “di luar hitungan”, rakyat yang terbungkam, yang bukan bagian dari himpunan, yang disisihkan untuk tak bisa ambil bagian.
Inilah tindakan yang disebut sebagai usaha menghidupkan kembali “Yang Politis” dari politik itu sendiri. Yang sekaligus sebagai sebuah upaya meniupkan kembali nyawa politik kaum muda yang telah mati dalam pasungan politik oligarki. Maka tantangannya, pemuda haruslah mampu berfikir out of the box, keluar dari mainstream politik transaksional dan politik kekerabatan, yang membuat politik mengalami menopause.
Kini tugasnya ialah melakukan “pembiasaan” (habituation) didalam komunitas politik yang digelutinya, yang kemudian melaluinya spirit dan visi politik sebagai pikiran dan politik sebagai perjuangan itu dibatinkan dan dicerminkan dalam tindakan sehari-hari.
Dari sinilah kemudian, sebuah habitus baru itu tercipta, sebuah budaya tandingan (counter-culture) dari arus mainstream politik saat ini itu eksis, yang darinya harapan, jalan perubahan dan kepemimpinan ideal itu dapat diciptakan, disemai dan direproduksi.