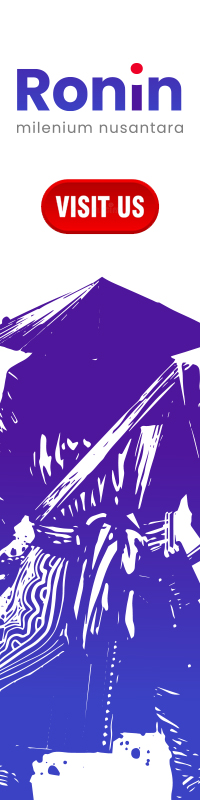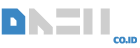Oleh: M. Nurfadillah
Mahasiswa Fisipol Universitas Yuppentek Indonesia
Setelah melalui proses legislasi yang panjang, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana nasional. Dewan Perwakilan Rakyat pada 18 November 2025 mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kemudian ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Desember 2025. Pemerintah menyatakan bahwa KUHAP akan berlaku beriringan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai awal 2026.
Pemberlakuan simultan KUHP dan KUHAP menandai dimulainya rezim hukum pidana baru. Namun, alih-alih semata menghadirkan kepastian hukum, sejumlah ketentuan justru memicu perdebatan publik. Sorotan utama tertuju pada pasal-pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, serta pengaturan unjuk rasa, yang dinilai berpotensi mempersempit ruang kebebasan berekspresi dan partisipasi warga negara dalam demokrasi.
Pemerintah beralasan bahwa ketentuan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan wibawa negara. Sebaliknya, kelompok masyarakat sipil menilai pasal-pasal ini menyisakan persoalan mendasar, terutama karena tidak adanya batas yang jelas antara kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana.
Dalam perspektif teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan Jürgen Habermas, ruang publik merupakan arena diskursif tempat warga negara menyampaikan kritik, pendapat, dan keberatan terhadap kebijakan negara secara rasional. Demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur elektoral, tetapi dari sejauh mana negara menjamin komunikasi bebas tanpa rasa takut. Ketika kritik berisiko dikriminalisasi, ruang publik mengalami distorsi, dan demokrasi kehilangan substansi deliberatifnya.
Secara konseptual, lembaga negara bukanlah entitas personal. Ia tidak memiliki perasaan, tidak dapat tersinggung, dan tidak memiliki hak subjektif untuk merasa terhina. Lembaga negara adalah entitas publik yang dibentuk oleh konstitusi, dibiayai oleh pajak rakyat, dan bekerja atas mandat warga negara. Dalam logika kontrak sosial ala John Locke, kekuasaan negara bersifat derivatif—berasal dari persetujuan rakyat—dan karenanya tunduk pada pengawasan serta kritik publik. Kritik bukan ancaman terhadap negara, melainkan bagian dari mekanisme akuntabilitas.
Persoalan muncul ketika kritik terhadap kebijakan atau kinerja lembaga negara berpotensi ditafsirkan sebagai penghinaan. Hingga kini, tidak tersedia ukuran yang benar-benar objektif dan terukur untuk membedakan keduanya. Pertanyaan krusialnya adalah siapa yang memiliki kewenangan menilai apakah suatu ekspresi merupakan kritik atau penghinaan.
Dalam kajian relasi kuasa dan hukum yang dikemukakan Michel Foucault, hukum tidak pernah sepenuhnya netral; ia beroperasi dalam jaringan kekuasaan. Ketika definisi “penghinaan” bersifat kabur dan aparat penegak hukum berada dalam struktur kekuasaan negara, maka hukum pidana berpotensi menjadi instrumen disiplin sosial. Kritik yang mengganggu stabilitas simbolik kekuasaan dapat dipersepsikan sebagai pelanggaran, bukan ekspresi politik yang sah.
Situasi ini semakin problematis di era digital. Media sosial, tulisan daring, dan ekspresi visual kini menjadi medium utama partisipasi warga negara. Namun, alih-alih dipandang sebagai bagian dari demokrasi partisipatoris, ekspresi digital justru berhadapan dengan ancaman pidana. Dalam perspektif teori chilling effect yang berkembang dalam studi hukum dan komunikasi politik, ancaman sanksi pidana tidak harus diterapkan secara masif untuk membungkam kebebasan; cukup dengan menciptakan ketakutan, warga akan melakukan sensor diri. Diam menjadi pilihan rasional di tengah ketidakpastian hukum.
Pengaturan unjuk rasa menunjukkan kecenderungan serupa. Hak menyampaikan pendapat memang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945, namun dalam praktiknya dibatasi melalui berbagai ketentuan administratif dan ancaman pidana. Demonstrasi tetap diakui sebagai hak, tetapi dengan prasyarat yang ketat. Kesalahan prosedural dapat berujung kriminalisasi, sementara dalam situasi keramaian atau kerusuhan, tanggung jawab kerap dibebankan kepada peserta aksi.
Kondisi ini sejalan dengan peringatan Hannah Arendt mengenai bahaya reduksi politik menjadi sekadar soal ketertiban. Dalam pandangannya, politik sejatinya adalah ruang pluralitas dan tindakan bersama. Ketika negara terlalu menekankan stabilitas dan ketertiban dengan mengorbankan kebebasan berekspresi, maka politik direduksi menjadi urusan administratif, bukan arena partisipasi warga negara.
Akibatnya, kebebasan berekspresi perlahan bergeser dari hak konstitusional menjadi aktivitas yang harus selalu aman di mata negara. Ruang publik dipenuhi kehati-hatian, dan demokrasi kehilangan salah satu elemen paling esensialnya: keberanian untuk berbeda pendapat.
Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri dari kritik, melainkan negara yang mampu berdiri kokoh di tengah kritik. Wibawa negara tidak lahir dari pembungkaman, tetapi dari kepercayaan publik yang dibangun melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan untuk dikoreksi.
Dengan mulai berlakunya KUHP hari ini, yang diuji bukan hanya efektivitas hukum pidana, melainkan juga kedewasaan demokrasi kita: apakah negara masih bersedia mendengar, dan apakah warga negara masih memiliki keberanian untuk bersuara.