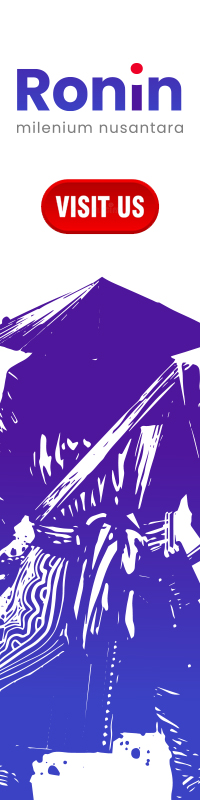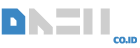Oleh: Junaidi Adinata
Praktisi BPR/Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute
Dunia perbankan sedang menyaksikan sebuah paradoks yang sunyi. Di satu sisi, narasi inklusi keuangan dan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) digaungkan dengan meriah di gedung-gedung tinggi Jakarta.
Namun, di sisi lain, di pelosok-pelosok daerah, “mesin” utama inklusi tersebut—Bank Perekonomian Rakyat (BPR)—justru berguguran satu per satu. Hingga pertengahan 2025, data OJK mencatat jumlah BPR/BPRS menyusut menjadi 1.518 unit. Sebanyak 261 unit bank sedang mencoba konsolidasi, merger, atau dibiarkan mati begitu saja.
Fenomena ini bukan sekadar angka statistik dalam laporan tahunan; ia adalah cermin dari kebijakan yang gagal menjadi menjadi enabler (pemandu) tumbuhnya sebuah industri.
Kematian BPR sering kali dipandang dingin sebagai “seleksi alam” atau konsekuensi logis dari efisiensi modal. OJK melaporkan sepanjang 2025 telah menyetujui konsolidasi sekitar 130 BPR.
Namun, jika kita membedah lebih dalam, ada kegelisahan yang mendasar: apakah kita sedang menyehatkan industri, atau justru sedang membiarkan institusi yang paling dekat dengan rakyat ini mati perlahan karena beban regulasi yang tidak proporsional?
Tujuan kelahiran BPR sangatlah luhur: menjadi jembatan bagi UMKM yang unbankable. Marr et al. (2020) dalam artikelnya di jurnal World Development, menyatakan, lembaga keuangan mikro (LKM) adalah instrumen kunci dalam mencapai target SDGs, khususnya pada aspek pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Di Indonesia, BPR melayani sekitar 14 juta nasabah. Dari situ, 10,5 juta di antaranya adalah debitur kecil yang mungkin tak akan pernah dilirik oleh bank umum raksasa.
Namun, daya hidup BPR kini terhimpit. Ada kebijakan “asimetris” melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Subsidi bunga KUR yang sangat rendah (6-7%) memang manis bagi rakyat, namun pahit bagi BPR.
Bagaimana mungkin sebuah BPR yang harus menghimpun dana masyarakat dengan bunga deposito tinggi mampu bersaing dengan bank umum yang disubsidi APBN? Strategi ini, tanpa disadari, telah “membajak” nasabah sehat BPR dan mendorong mereka ke arah ketergantungan pada bank besar.
Lalu, beban regulasi kini kian “seragam” dengan bank umum. Kewajiban modal inti minimum Rp6 miliar dan penerapan standar tata kelola (GCG) yang kaku sering kali menjadi beban administratif yang sangat mahal bagi BPR di tingkat kecamatan.
Menurut Cull et.al (2011) dalam jurnal Banking & Finance, regulasi yang terlalu membebani biaya operasional, tanpa mempertimbangkan jangkauan sosial, justru akan menghambat kemampuan lembaga keuangan kecil dalam melayani masyarakat miskin.
Di sinilah letak titik krusialnya. Pemerintah dan OJK tidak boleh hanya berhenti pada fungsi pengawasan dan eksekusi. Ada fungsi fundamental pemerintah sebagai enabler yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan ekosistem BPR.
Pemerintah dan otoritas harus menjadi fasilitator infrastruktur teknologi bersama. Digitalisasi adalah keniscayaan, namun harganya mahal. Schulz & Scharfenberg (2021), dalam jurnal Small Business Economics, menekankan bahwa transformasi digital adalah kunci resiliensi LKM di tengah guncangan teknologi.
Pemerintah harus hadir membangun shared services—infrastruktur IT kolektif yang dikelola oleh negara (misalnya melalui LPS atau Bank Indonesia)—sehingga BPR kecil tidak perlu membangun server sendiri yang bernilai miliaran. Dengan sistem berbagi ini, BPR bisa memiliki layanan mobile banking dan standar keamanan siber yang setara dengan bank besar tanpa harus bangkrut karena biaya investasi teknologi.
Selain itu, otoritas harus memperkuat fungsi supervisi edukatif. Sebagian besar kegagalan BPR bersumber dari kelemahan manajemen dan risiko fraud. Otoritas perlu menyediakan program sertifikasi gratis dan berkelanjutan bagi pengurus BPR, serta membangun sistem peringatan dini (Early Warning System) yang tidak berujung pada penutupan, melainkan pada bantuan manajemen sementara untuk menyehatkan kembali bank yang mulai limbung.
Konsolidasi Jangan Dipaksakan
Pemerintah juga bisa mempertimbangkan lagi skema penyaluran kredit program. Alih-alih menjadikan BPR sebagai penonton dalam penyaluran KUR, pemerintah mestinya dapat memposisikan BPR sebagai mitra utama penyaluran di daerah terpencil melalui skema linkage yang lebih adil.
Subsidi bunga seharusnya juga diberikan kepada BPR yang menyalurkan kredit kepada sektor produktif, sehingga level playing field antara bank umum dan BPR menjadi seimbang.
Khan et al. (2022) dalam jurnal Sustainability, menyatakan, lembaga keuangan kecil lebih efektif dalam menyalurkan “kredit hijau” di tingkat tapak.
Pemerintah harus memberikan insentif khusus, misalnya pelonggaran pajak atau kemudahan likuiditas, bagi BPR yang fokus membiayai usaha ramah lingkungan seperti pertanian organik atau energi terbarukan skala mikro. Ini akan menyelaraskan fungsi ekonomi BPR dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional.
Hapus pula anggapan bahwa BPR adalah “bank kelas dua”. Pemerintah perlu melakukan kampanye nasional bahwa tabungan di BPR aman dan dijamin LPS. Selain itu, keterlibatan BPR dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) atau dana desa secara digital akan meningkatkan profil dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.
Membiarkan BPR mati satu per satu berarti memutus urat nadi ekonomi lokal. Morgan & Pontines (2014) dalam International Review of Economics & Finance, menegaskan, bank lokal berkontribusi besar pada stabilitas keuangan nasional karena sifatnya yang resisten terhadap guncangan pasar modal global. Namun, konsolidasi yang dipaksakan tanpa adanya pendampingan hanya akan menciptakan bank-bank hasil merger yang tetap lemah secara inovasi.
Indikator kesehatan seperti CAR minimal 8% atau LDR di kisaran 78-92% adalah standar yang harus dipenuhi, namun angka-angka tersebut tidak ada artinya jika BPR kehilangan jiwa personalnya.
Kekuatan utama BPR adalah pendekatan “5C” (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) yang dilakukan secara humanis, mengenal nasabah hingga ke ruang tamu mereka. Sentuhan manusiawi inilah yang tidak dimiliki oleh algoritma fintech maupun bank digital raksasa.
Masa depan Bank Perekonomian Rakyat berada di persimpangan jalan. Kita butuh BPR yang sehat secara finansial, namun kita lebih butuh regulator yang visioner. Transformasi BPR tidak akan berhasil jika pemerintah hanya menjadi “penjaga gerbang” yang memegang kunci likuidasi.
Regulator harus berani mengotori tangan dengan masuk ke dalam proses pembinaan yang lebih dalam. Kita membutuhkan kebijakan yang afirmatif, bukan sekadar administratif. Merawat BPR adalah merawat harapan jutaan pedagang pasar, petani, dan pengusaha mikro yang selama ini menjadi mesin penggerak ekonomi riil Indonesia.
Jangan sampai saat kita terlalu asyik mengejar efisiensi di atas kertas, kita justru kehilangan jangkar ekonomi yang selama ini menjaga stabilitas di akar rumput. Dalam ekonomi, pertumbuhan adalah keharusan, namun keadilan dan inklusi adalah kehormatan. Dan BPR adalah tentang kehormatan ekonomi rakyat.