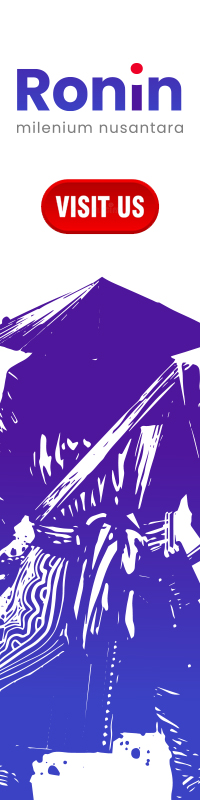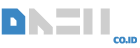Oleh: Iswandi
Praktisi Perbankan/Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute
Perbankan digital di Indonesia tidak lagi berada dalam fase eforia “bakar uang” untuk sekadar mengakuisisi pengguna. Di tahun 2026, industri ini harus bergeser ke arah kedewasaan. Kemampuan menghasilkan laba harus menjadi indikator kelangsungan hidup.
Apalagi, proyeksi “e-Conomy SEA” (Google, Temasek, Bain & Company) menunjukkan bahwa jumlah pengguna bank digital akan menyentuh angka 75 juta jiwa atau mencakup sekitar 39 persen dari populasi Indonesia
Namun, industri ini juga harus menghadapi ancaman suhu bumi yang terus meningkat dan volatilitas pasar yang dipicu oleh fragmentasi geopolitik.
Tak ayal, bank digital kini dituntut untuk membuktikan bahwa model bisnis nir-kantor mereka bukan sekadar cara efisien untuk memindahkan uang, melainkan instrumen yang mampu memitigasi risiko sistemik dari perubahan iklim.
Temelkov (2020), dalam Journal of Economics, menyatakan, pergeseran struktur biaya perbankan digital seharusnya memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk mendanai transisi ekonomi hijau. Namun, kenyataannya, efisiensi tersebut sering kali ditelan biaya akuisisi nasabah yang tidak setia dan investasi keamanan siber yang tidak berkesudahan.
Proyeksi kenaikan nasabah itu juga bisa menciptakan paradoks profitabilitas yang mengkhawatirkan. Pendapatan bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM) terus mengalami tekanan akibat normalisasi suku bunga dan persaingan sengit dengan bank konvensional raksasa yang telah bertransformasi secara total.
Pertumbuhan laba industri yang diprediksi tertahan di angka 5 persen (YoY) adalah alarm bagi para investor yang mulai menuntut dividen nyata, bukan sekadar janji pertumbuhan basis pengguna.
Dalam kaitan dengan pembangunan berkelanjutan, bank digital harus segera beralih dari sekadar memfasilitasi konsumsi ritel menuju pembiayaan sektor produktif yang ramah lingkungan.
Mejia-Escobar et al. (2020), dalam jurnal Sustainability, mengingatkan bahwa produk keuangan berkelanjutan, seperti pembiayaan mikro untuk energi terbarukan, adalah kunci untuk menciptakan loyalitas nasabah jangka panjang sekaligus membangun portofolio yang tahan terhadap risiko transisi karbon.
Regulasi di tahun 2026 pun semakin tidak kompromistis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mewajibkan standar transparansi yang jauh lebih ketat, terutama terkait pemenuhan modal inti Rp6 triliun.
Bagi bank digital kecil yang belum mencapai skala ekonomi, pilihannya hanya dua: melakukan konsolidasi atau perlahan menghilang dari peredaran. Kewajiban ini sebenarnya merupakan berkah tersembunyi untuk membersihkan pasar dari pemain yang hanya mengandalkan spekulasi tanpa fundamental yang kuat.
Hornuf et al. (2021) dalam Small Business Economics, menegaskan, keberhasilan bank digital di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk berintegrasi ke dalam ekosistem embedded finance yang memiliki dampak sosial nyata.
Bukan sekadar menjadi dompet digital untuk transaksi konsumtif. Transformasi ini menjadi krusial mengingat sektor keuangan adalah jantung dari distribusi modal nasional yang harus diarahkan pada target Net Zero Emission Indonesia.
Dari sisi operasional, tantangan keamanan siber di tahun 2026 telah berevolusi menjadi ancaman berskala nasional. Dengan pertumbuhan transaksi pembayaran digital yang melesat 29,7 persen, bank digital menjadi sasaran empuk serangan siber berbasis kecerdasan buatan dan potensi ancaman kriptografi pasca-kuantum.
Keamanan bukan lagi soal autentikasi dua faktor sederhana, melainkan soal perlindungan kedaulatan data nasabah yang menjadi aset paling berharga dalam ekonomi digital. Ketidakmampuan menjaga data pribadi bukan hanya akan berujung pada denda regulasi yang berat sesuai UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), tetapi juga akan meruntuhkan seluruh narasi pembangunan berkelanjutan yang diusung.
Menruut Gomber et al. (2018) ,dalam Journal of Management Information Systems, inovasi teknologi finansial harus menempatkan integritas sistem sebagai pilar utama keberlanjutan ekonomi. Tanpa keamanan yang mumpuni, inklusi digital hanyalah sebuah ilusi yang membahayakan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Literasi adalah Kunci
Pembangunan berkelanjutan dalam perbankan digital juga berarti menyentuh aspek literasi finansial yang masih menjadi problem di Indonesia. Kemudahan akses yang ditawarkan teknologi sering menjadi pedang bermata dua; membuka akses modal bagi masyarakat pedesaan sekaligus menjebak mereka dalam siklus utang tidak sehat jika tidak dibarengi edukasi yang memadai.
Bank digital memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan fitur edukasi dan pengelolaan keuangan otomatis pada aplikasinya.
Abbasi et al. (2021) dalam jurnal Sustainability menekankan bahwa korelasi antara adopsi teknologi finansial dan pembangunan berkelanjutan hanya akan positif jika teknologi tersebut mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat kelas bawah secara riil.
Penggunaan Artificial Intelligence (AI) seharusnya diarahkan untuk mendeteksi potensi gagal bayar nasabah secara dini dan memberikan solusi restrukturisasi yang manusiawi, alih-alih digunakan untuk penagihan yang agresif.
Sinergi antara kebijakan hijau pemerintah dengan inovasi bank digital harus semakin erat. Implementasi fitur carbon footprint tracker yang terhubung dengan setiap transaksi nasabah bukan lagi sekadar tren, melainkan standar industri untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat.
Bank digital yang mampu menyalurkan kredit hijau (green loans) dengan suku bunga yang lebih kompetitif bagi pelaku UMKM yang menerapkan praktik ramah lingkungan akan memiliki keunggulan kompetitif yang tak tertandingi.
Penguatan permodalan melalui konsolidasi harus diarahkan untuk menciptakan bank digital berskala besar yang memiliki “otot” finansial untuk masuk ke pembiayaan transisi energi berskala menengah.
Masa depan perbankan digital Indonesia di tahun 2026 tidak akan ditentukan oleh seberapa canggih algoritma yang dimiliki, melainkan oleh seberapa besar keberaniannya untuk membiayai masa depan bumi yang lebih layak huni.
Dinamika 2026 juga akan mempertegas jurang antara bank digital besutan konglomerasi perbankan dengan entitas independen. Kelompok pertama menikmati kemewahan biaya dana (cost of funds) rendah berkat kepercayaan warisan (legacy trust).
Kelompok independen terjepit antara ambisi inovasi dan kewajiban pemenuhan modal inti Rp6 triliun. Neobank independen kini dipaksa mencari ceruk pasar spesifik guna menghindari kanibalisasi oleh ekosistem raksasa konvensional yang kian lincah berselancar di ruang siber.
Yang jelas, perbankan digital harus berhenti memandang aspek keberlanjutan sebagai biaya tambahan atau sekadar laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Di tengah krisis iklim yang nyata dan ketidakpastian internasional, prinsip ESG adalah satu-satunya navigasi yang valid untuk memastikan resiliensi bisnis.
Transformasi menuju bank digital yang hijau, transparan, dan aman adalah jalan tunggal untuk keluar dari ilusi pertumbuhan yang semu. Perbankan digital harus menjadi mesin yang menggerakkan kemakmuran tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Jika sinergi antara inovasi teknologi dan keberlanjutan ini gagal dibangun, maka pertumbuhan 75 juta pengguna hanyalah statistik hampa yang menunggu waktu untuk runtuh. Ketangguhan ekonomi bangsa di masa depan sangat bergantung pada transformasi fundamental yang dilakukan oleh para pemain perbankan digital hari ini.