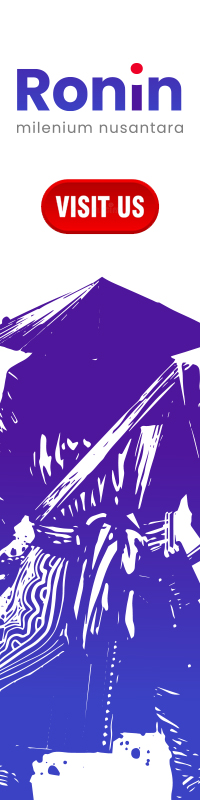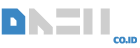Oleh: Indra J Pilliang
Profesor Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam dua hari ini mendapatkan serangan dari netizen. Pada hari Rabu kemaren, Detik.com memuat berita yang berisi wawancara blak-blakan dengan beliau. Satu kalimat menjadi diperbincangkan.
“Jadi, kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu, ya, agama, bukan kesukuan,” begitu penggalannya.
Langsung saja, para pesohor di ranah media sosial, terutama twitter, “menyambiti” wawancara itu. Per pagi ini saja, berita itu dikomentari oleh sekitar 670 orang dalam kolom komentar. Jumlah yang luar biasa, hanya dalam waktu satu kali 24 jam. Tentu, mayoritas bernada berang alias tidak setuju.
Pancasila lahir dari sebuah kesepakatan para pendiri bangsa (the founding fathers and mothers). Kesepakatan yang dicapai pada tahun 1945 itu sama sekali tak bulat. Sampai tahun 1959, singa-singa podium dalam Dewan Konstituante masih bersitegang leher. Dekrit Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengakhiri sesi perdebatan yang paling legendaris itu.
Dewan Konstituante sebetulnya sudah selesai menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru, sebagai pengganti dari UUD 1945. Rumusan UUD hasil karya Dewan Konstituante itu termasuk yang paling sulit dicari tandingannya di muka bumi. Dari sisi sistematika pasal dan ayat saja, terbaca betapa hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara lebih didahulukan, ketimbang bentuk negara.
Padahal, dibandingkan dengan UUD Amerika Serikat, misalnya, UUD 1945 jauh lebih moderen. Declaration of Human Right yang muncul tahun 1945 itu, langsung diadopsi oleh pendiri bangsa. Bak kue yang masih hangat dari panggangan (oven), sulit sekali menemukan rumusan hak asasi manusia itu dalam konstitusi negara-negara lain.
Padahal, UUD 1945 hanya disusun beberapa bulan saja. Bayangkan UUD yang disusun oleh Dewan Konstituante. Mereka berdebat selama kurang lebih empat tahun. Media massa begitu hiruk-pikuk. Apalagi, partai-partai politik memiliki corongnya sendiri-sendiri, yakni media massa harian, mingguan, hingga bulanan.
Perdebatan tak hanya terjadi di podium. Namun juga sepanjang perjalanan menuju podium, sampai pulang ke rumah masing-masing. Saking asyiknya berdebat, IJ Kasimo sering masuk hingga ke dapur Mohammad Natsir. Perut yang lapar selama berdebat, tentu perlu diisi dengan segelas kopi, ditambah gorengan.
Dewan Konstituante hanya belum sepakat tentang Dasar Negara Republik Indonesia. Belum sepakat yang tak bermakna 100 persen. Kesepakatan-kesepakatan besar, menengah dan kecil sudah berhasil didapat. Rumusan hukum (legal drafting) tentang dasar negara itu sama sekali masih berupa pilihan kalimat demi kalimat. Jika saja waktu minum kopi di dapur masing-masing singa podium itu diperbanyak dan diperpanjang, sejarah bakal ditulis ulang.
Pengaruh geopolitik kala itu ternyata tak berujung kepada kesepakatan holistik. Panggung Dewan Konstituante dianggap terlalu berisik. Tak tanggung-tanggung, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memundurkan Indonesia yang masih muda itu 14 tahun ke belakang. Indonesia kembali ke UUD 1945.
Baiklah, kalaupun hanya perdebatan tahun 1945 yang dijadikan acuan, tetap saja bisa dilacak apa yang dimaksud sebagai musuh Pancasila. Tidak perlu membandingkan pikiran Sukarno dengan pikiran tokoh-tokoh lain, terutama dari Sumatera Barat. Rujuk saja Sukarno.
Apa yang ia katakan?
Pancasila bisa diperas menjadi Trisila, yakni sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan (baca: teisme). Bahkan, Trisila bisa menjadi Ekasila, yakni kegotong-royongan.
Apa musuh Trisila? Tentu saja kolonialisme, kediktatoran (bisa atas nama monarki, bisa juga berupa teokrasi, bahkan feodalisme dalam bentuk yang paling tribal), dan ateisme.
Sementara musuh Ekasila? Individualisme, egosentrisme, bahkan bisa juga heroisme produksi Hollywood. Avengers yang tak melibatkan Gundala, Godam, hingga Si Buta Dari Gua Hantu dapat disebut sebagai musuh Ekasila ini!
Ketika Profesor Yudian Wahyudi menyebut agama (teisme) sebagai musuh Pancasila, terasa sekali contradictio in terminis dalam konteks filsafat ilmu pengetahuan yang membentuk rumusan-rumusan Pancasila. Teisme tidak mungkin berhadapan dengan Pancasila, baik dari sisi spiritualitas yang hidup di bumi nusantara, maupun kandungan isi dari kitab-kitab suci dalam agama-agama samawi. Kaum penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa saja, baik dalam bentuk tungga atau politeis, masih percaya kepada sesuatu yang transendental atau supra natural.
Baik raja, pendekar, hingga bandit semacam Ken Arok, selalu menempelkan nama-nama yang diluar manusia sebagai deklarasi diri. Monas, misalnya, adalah alat kelamin Dewa Siwa dan Dewi Uma, satu lingga, satu yoni, namun tetap bernilai spiritual ketimbang sanggama. Beratus situs arkeologi hingga sejarah memberi petunjuk betapa terdapat kekuatan ghaib yang diluar kemampuan manusia sebagai pesan terkuatnya.
Bisa saja, Profesor Yudian Wahyudi tak lengkap menjelaskan maksud dari kalimatnya. Sebagaimana juga Sukarno yang hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam risalah rapatnya. Toh Sukarno terus mencoba untuk memberikan pemahaman yang sesederhana mungkin, termasuk dalam penugasan sejumlah tim pascaproklamasi. Tim yang membuat Lambang Negara, misalnya. Atau tim yang menarasikan bendera Sang Saka Merah Putih.
Mohammad Yamin perlu menerbitkan buku “600 Tahun Sang Merah Putih” yang jauh dari selesai pada tahun 1953. Kesimpulan betapa Sang Merah Putih adalah bendera yang dipakai pasukan Jayakatwang (Kediri) dalam menghadapi Kartanegara (Singosari) masih bisa dipertanyakan. Bagaimana mungkin Indonesia menggunakan bendera “kaum pemberontak” dalam makna Singosari? Belum lagi misteri dibalik ketakutan para penguasa untuk hadir ke Kediri, dari Indonesia kuna hingga Indonesia abad ke-21 sekarang. Bendera Kediri dipakai sebagai sang saka, sementara tanah Kediri tak hendak untuk diinjak sang penguasa negeri.
Jangan-jangan, musuh Pancasila itu adalah kalangan pengusaha sendiri. Yang tak mendedahkan Pancasila sebagai mata air ilmu pengetahuan, tetapi justru mantra penuh kutukan. Jangan heran, kalau Profesor Yudian Wahyudi lebih tampak bak dukun-dukun dari hutan rimba dengan jampi-jampinya, ketimbang guru besar yang sudah menyelesaikan mata kuliah logika, hermeneutika dan tata bahasa.