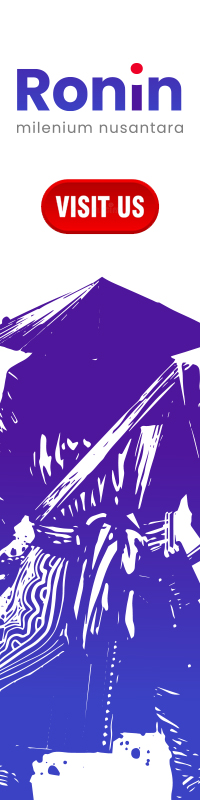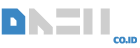Oleh: Yul Amrozi
(Pernah menjadi mahasiswa yang menjadi tahanan politik selama 5 hari di Kodim Sleman Yogyakarta pada Agustus 1996)
Salah satu peristiwa paling anekdotal sekaligus mendebarkan dalam sejarah Republik Indonesia adalah “penculikan” Rengasdengklok. Sebut saja beberapa nama yang muncul di Wikipedia, seperti Sukarni, Wikana, Aidit, Chaerul Saleh, dan Adam Malik dari kelompok Menteng 31 yang letaknya di Cikini Raya itu semuanya adalah teman seangkatan umur mereka hampir sama.
Semuanya lahir di tahun 1914 hingga 1917, kecuali Aidit yang lebih muda karena lahir 1923. Prestasi mereka dalam catatan sejarah yang ada dalam buku “masterpiece”nya Soe Hok Gie (Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, 1997) adalah mengorganisir tukang becak di sekitar Cikini dan Gondangdia Lama.
Umur mereka pada waktu itu tentu saja umur ‘aktivis’ mahasiswa. Kurang di bawah 30 tahun. Apakah yang mereka lakukan dengan menculik politisi senior yang umurnya di atas 40 tahun, tentu saja bukan sesuatu yang “luar biasa” jika kita melakukan “retroprojeksi” dengan kultur yang ada di “pergaulan” para “aktivis ibukota” yang cukup marak sejak Reformasi 98.
Bahwa jarak umur 10 sampai 20 tahun dengan generasi senior itu bukan sesuatu yang menjadi persoalan dalam sejarah politik Republik. Kalau kemudian sampai hari ini “kawan” senior seperti Bang Hariman (kelahiran 1950, masih kenal dengan si Gilbran (kelahiran tahun 2000), yang viral dengan mengatakan Jokowi sebagai alumni UGM yang memalukan tentu saja hal itu harus dipahami sebagai budaya politik “khas” Indonesia.
Mahasiswa entah kenapa selalu menjadi takdir politik Indonesia. Entah mengapa republik beriklim tropis yang luasnya seukuran seluruh benua Eropa dalam sejarah suksesi politik baik itu melalui jalan paksa atau bergilir selalu melibatkan kelompok sosial berusia muda, “bersekolah”, anak dari kelompok sosial menengah di zamannya yang membuat dinamika dalam setiap tikungan sejarah perpindahan generasi.
Masih ingat “dongeng” Babat Tanah Jawa tentang Karebet yang mempunyai kemampuan “lompat mundur” sepanjang kolam keraton Demak. Dikisahkan pada dongeng itu kalau Karebet ini adalah anak muda yang punya sebutan “putut” (mahasiswa di zaman jawa mataram) dengan kemampuan bersilat yang luar biasa.
Jadi, bergembiralah, karena buat mereka yang berusia antara 20 hingga 40 dalam beberapa waktu ke depan, dalam pergantian kekuasaan yang sudah pasti akan berlangsung, jika mereka mempunyai rekam jejak sebagai ‘aktivis’ mahasiswa pasti akan mendapat tempat. Tetapi, bukankah populasi mahasiswa sebagai salah satu “kelompok strategis” (Hans Dieter Evers 1990) semakin hari semakin banyak.
Apakah peluang untuk mendapat tempat masih bisa seperti dulu, seperti seorang Siswono Yudo Husodo atau Sarwono Kusumaatmadja (kedua-duanya kelahiran 1943) yang bisa dipilih oleh Soeharto untuk duduk dalam jajaran Kabinet Pembangunan V.
Konon seorang Sarwono harus mau loh untuk menjadi Menteri Muda, walaupun harus di bawah todongan senjata (rumor). Tetapi kisah-kisah luar biasa di setiap tikungan sejarah Republik sebenarnya tidak kurang-kurang. Masih ingat penyelundup jam Rolex untuk perwira-perwira Dai Nippon yang dimodali oleh seorang manajer perusahaan kapal pesiar terbesar di dunia saat itu bisa menjadi seorang wakil presiden dari seorang Presiden yang dikenal sebagai pembasmi kaum Komunis.
Padahal penyelundup yang suka mengambil barang di Pelabuhan Tanjung Priok itu tak lain tak bukan adalah aktivis sebuah partai “Komunis” yang mengusung nama Musyawarah Rakyat Banyak. Ironi yang sangat “ironis”.
Kalau merunut pada rekam jejak, penyelundupan arloji mewah, untuk mendapatkan duit cepat di masa “bersiap” tentu bukan hal yang terpuji. Tetapi, peduli setan.
Kalau Angrok bisa membuat Kebo Ijo pamer keris pusaka, yang membuat dia menjadi tertuduh nomor satu atas pembunuhan sang adipati Tumapel, kenapa harus bicara soal baik dan buruk. Kalau Karebet bisa bersekutu dengan “Siluman Buaya” untuk membumihanguskan kesultanan Demak Bintoro kenapa harus bicara tentang “gerakan moral”.
Gerakan Moral, jika dipikir sebagai istilah yang lazim digunakan orang kebanyakan mungkin akan menjadi “oxymoron”. Karena yang bergerak itu orang, sementara moral ya moral dia di awang-awang. Memang bergerak tetapi dalam sebuah “super struktur” (kalau mengutip kajian Hegelian).
Dalam faktanya, aktor-aktor politik Indonesia selalu lahir dari lingkaran-lingkaran perkoncoan yang sebenarnya saling mengenal. Masih ingat, kajian para peneliti Indonesianis yang bingung membuat kategori politik seperti apa yang terjadi dalam cara bernegara orang-orang yang sejak zaman pertemuan pedagang antar samudera sudah mempunyai jejak heterogenitas yang bertebaran.
Jika ingin berkuasa, buatlah gerakan politik bukan gerakan moral. Dan itu pernah dipraktikkan oleh sekelompok kecil mahasiswa di Indonesia dari beberapa kota yang ada universitas negerinya (medan, bogor, jakarta, semarang, jogja, solo, surabaya) pada pertengahan 90-an. Jelas, yang dibuat adalah partai politik.
Soal menang atau tidak dalam kontestasi pemilu itu nomor 27. Faktanya beberapa gelintir anak muda 90-an itu menjadi “top of mind” ketika politik Indonesia, yang belakangan tidak begitu menggembirakan, untuk duduk dalam kursi-kursi “hulubalang” republik. Apa rahasianya, ya bergerak, berkumpul, berorganisasi, kemudian aksi (sukur-sukur dipenjara) dengan ajukan program-program politik yang RELEVAN pada zamannya. Soal program politik itu akan berkembang menjadi apa biarkan saja waktu yang menentukan (Betara Kala).
Gambaran di atas bagi yang berpikiran positif tentu terasa “absurd”. Tetapi takdir politik Indonesia memang penuh enigma. Eyang Denys Lombard, yang punya tiga buku Nusajawa saja pada tahun-tahun terakhir masa hidupnya, memilih untuk mengikuti laku yang dicontohkan Gus Dur, rajin ke makam wali.
Eyang Peter Carey, yang hampir seumur hidup akademis dia mengaduk-aduk arsip Diponegoro saja selalu bilang kalau politik orang Indonesia ini sudah sangat kosmopolit bahkan di zaman kedatangan bandar-bandar Eropa yang baru merasa memiliki semangat etnografi untuk mengupas bangsa yang dipikirnya “hanya bercelana kain blacu, tanpa berbaju”.
Faktanya, walaupun tidak merata di kalangan “warga negara” politik bernegara di Jawa, Sumatera, Bugis, hingga Maluku dan Halmahera sudah memiliki banyak hulubalang yang berusia muda yang sudah paham bahwa peta Mercator itu adalah peta yang sama seperti digambarkan oleh Karaeng Pattingalloang.
Maka tidak heran bila sang Orientalis akbar yang bernama Snouck Hurgronje, merasa perlu untuk membagi semua harta warisannya secara merata kepada semua anak-anaknya. Baik itu untuk istri dari Belanda, dari Mesir, dari Yaman, dari Cianjur, Tasikmalaya, atau Magelang. Semua mendapat bagian yang sama rata.
Konon jumlahnya masing-masing 5000 Gulden. Karena semua pencapaian besar dan satu-satunya etnolog yang bisa sampai ke Haramain tanpa kehilangan nyawanya, hanya bisa didapat ketika dia harus mau menjadi mahasiswa dari Mufti Syafii terkemuka yang ada di Mekkah. Dia juga harus mau berbagi peran dengan sesama mahasiswa yang berasal dari Pandeglang yang bernama Abu Bakar Djajadiningrat.
Dari seorang mahasiswa bernama Abu Bakar inilah masa tinggal Snouck yang pendek di Mekkah (hanya 6 bulan) bisa dikompensasi dengan korespondensi yang terus menerus dari 1880-an sampai 1930-an.
Dari balas jasa terhadap anak keturunan hulubalang Kerajaan Banten itulah bea siswa bagi mahasiswa-mahasiswa Hindia Belanda di Leiden berasal. Dan sisanya adalah sejarah yang memperlihatkan mahasiswa-mahasiswa anak didik Leiden yang kemudian banyak menjadi perintis pergerakan menuju Republik Indonesia.